Kesadaran beragama dalam konteks Rusia modern. Kekhasan kesadaran beragama. Peran dan fungsi agama. Situasi keagamaan di dunia modern Sarana pembentukan kesadaran beragama di dunia modern
Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial
Departemen Antropologi Filsafat
PEKERJAAN LULUSAN
Struktur dan ciri-ciri kesadaran beragama umat modern di Rusia
Perkenalan
Bab 1 Kesadaran Beragama: Kemunculan, Esensi, Struktur, Ciri-ciri
1.1 Kondisi dan faktor munculnya kesadaran beragama
1.2 Esensi dan struktur kesadaran beragama
Bab 2 Ciri-ciri penting kesadaran keagamaan umat beriman di Rusia modern
2.1 “Kebangkitan” kesadaran beragama di Rusia
2.2 Religiusitas semu sebagai ciri kesadaran beragama umat modern
Kesimpulan
Daftar sumber yang digunakan
anotasi
Berdasarkan analisis literatur dalam dan luar negeri tentang topik ini, penulis mengkaji struktur dan ciri-ciri perkembangan kesadaran beragama umat beriman di Rusia modern. Artikel tersebut membahas tentang kondisi dan faktor terjadinya, struktur, tingkatan, alasan kebangkitan religiusitas di Rusia saat ini. Penulis berkesimpulan bahwa dalam dimensi sosiokultural, agama sebagai sebuah tradisi telah kehilangan tujuan sebenarnya dan saat ini pseudo-religiusitas semakin menguat posisinya. Objek penelitiannya adalah keadaan kesadaran keagamaan modern orang Rusia.
Anotasi
Berdasarkan analisis literatur dalam dan luar negeri tentang subjek ini penulis mengkaji struktur dan ciri-ciri perkembangan kesadaran beragama umat beriman di Rusia modern. Artikel ini mengkaji kondisi dan faktor struktur, tingkatan, penyebab kebangkitan agama di zaman kita di Rusia. Penulis berkesimpulan bahwa dalam dimensi sosio-kultural, agama sebagai sebuah tradisi telah kehilangan makna sebenarnya, dan saat ini yang semakin kuat kedudukannya adalah agama semu. Objek studinya adalah keadaan kesadaran keagamaan modern orang Rusia.
Perkenalan
Proses transformasi masyarakat Rusia pada pergantian abad XX-XXI. - Perubahan ekonomi, sosial, dan budaya yang pesat ini juga membawa perubahan pada isi semua bidang kesadaran masyarakat, yang mengarah pada peningkatan spiritualitas masyarakat, kebangkitan nilai-nilai agama dan pembentukan kesadaran keagamaan yang baru secara kualitatif. Hal ini menentukan relevansi topik penelitian.
Kesadaran beragama merupakan salah satu sistem pandangan dunia yang memperkuat masyarakat pada masa stabilitas dan dapat berubah pada masa perubahan sosial yang signifikan. Kesadaran beragama mampu mempengaruhi masyarakat dan berperan aktif dalam pembentukan nilai-nilai spiritual, pandangan dunia, dan pelestarian tradisi. Ia menjalankan dua fungsi yang berlawanan dalam masyarakat: di satu sisi, ia membedakan masyarakat menjadi dua kubu: beriman dan tidak beriman, dan di sisi lain, ia mengintegrasikan dan mempersatukan.
Periode penindasan terhadap agama yang sangat lama di Rusia dan aktivitas keagamaan selanjutnya berkontribusi pada penyebaran sekte totaliter, sentimen keagamaan fundamentalis dan ekstremis. Fenomena pseudo-religiusitas sudah meluas.
Meskipun saat ini terdapat banyak literatur tentang masalah agama, namun fenomena kesadaran beragama masih belum banyak diteliti. Penelitian ke arah ini dilakukan terutama dalam kerangka kajian agama. Situasi teoritis-kognitif yang berkembang dalam bidang kajian permasalahan kesadaran beragama menimbulkan sejumlah permasalahan metodologis dan teoretis yang memerlukan pemahaman sosial dan filosofis.
Mengatasi masalah ini juga relevan karena meningkatnya peran sosial agama dalam kehidupan masyarakat Rusia secara keseluruhan, karena agama mulai dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai penjaga kebenaran tentang hal-hal yang paling umum. hukum keberadaan. Setelah penghapusan tabu ideologis, yang tidak mengizinkan pendekatan lain terhadap kajian agama selain pendekatan materialis, kebutuhan untuk mengembangkan landasan filosofis dan ideologis baru dalam kajian kesadaran beragama menjadi jelas.
Adapun sejauh mana perkembangan topik tersebut, karya sejumlah peneliti telah dikhususkan pada masalah menganalisis esensi kesadaran beragama dan mengidentifikasi kekhususannya.
Di antara para filsuf dalam dan luar negeri yang membahas masalah esensi, isi dan tipologi kesadaran beragama, tempatnya dalam struktur kesadaran sosial, nama-nama berikut dapat disebutkan: Borunkov Yu.F. "Struktur kesadaran beragama", "Fitur dari kesadaran beragama”; Lobovik B. A. “Kesadaran beragama dan ciri-cirinya”; Yablokov I. N. "Studi Keagamaan" dan lainnya.
Kepercayaan terhadap supranatural dianalisis secara rinci dalam karya E. Durkheim “On the Division of Social Labour”, dan N.A. Berdyaev menaruh perhatian besar pada masalah keyakinan agama. “Kesadaran beragama dan masyarakat baru”; Ilyin I.A. "Aksioma Pengalaman Beragama"; Soloviev V. S. “Soloviev V. S. Awal filosofis dari pengetahuan integral”, “Bacaan tentang Kemanusiaan Tuhan; Landasan spiritual kehidupan; Pembenaran yang baik"; James W. “Varietas Pengalaman Religius” dan lain-lain.
Kondisi dan faktor munculnya kesadaran beragama serta tingkatannya diulas secara luas dalam karya-karya Weber M. “Selected. Citra masyarakat”, Borunkova Yu.F. “Fitur kesadaran beragama” dan “Struktur kesadaran beragama”; Subbotina N. D. “Sosial di Alam. Alami dalam sosial”; Gavrilova Yu.V. “Sistem faktor alam dalam pembentukan kesadaran beragama”; Shikhova G. L. "Rasa sakit dalam ritual"; Shaforostova A.I. "Iman sebagai cerminan realitas"; Lektorsky V. A. “Kesadaran // Ensiklopedia Filsafat Baru”; Pyrina A. G. “Lingkungan alam (analisis sosio-filosofis).”
Kebangkitan kesadaran beragama di penghujung abad ke-20. dianalisis secara rinci: Mchedlov M.P. “Politik dan Agama”; Uledov A.K. “Kehidupan spiritual masyarakat: Masalah penelitian metodologis”; Huntington S. “Bentrokan Peradaban”; Zhuravlev V.V. “Masalah kehidupan spiritual masyarakat”; Kimelev Yu.A. “Filsafat Agama Barat Modern.”
Orang-orang berikut ini menulis dalam karyanya tentang keadaan dan ciri-ciri kesadaran beragama umat modern: Rozin V.M. “Ajaran dan praktik mistik dan esoteris di media”; Mol A. “Sosiodinamika budaya”; Mchedlov M. P. “Tentang potret sosial orang percaya modern”; Novikova L.G. “Ciri-ciri utama dinamika religiusitas penduduk”; Vorontsova L.M. “Agama dalam kesadaran massa modern”; Andrianov N.P. “Ciri-ciri kesadaran beragama modern”, mereka juga melakukan banyak studi sosiologis tentang keadaan kesadaran beragama.
Objek penelitian ini adalah kesadaran beragama.
Subyek kajiannya adalah religiusitas, indikator tingkat dan isinya, serta tren perkembangan kesadaran beragama orang Rusia saat ini.
Maksud dan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis esensi kesadaran keagamaan orang Rusia dan tren perkembangannya.
Dalam hal ini, kita dihadapkan pada tugas-tugas berikut:
Menggali kekhususan, hakikat, struktur, tingkat kesadaran beragama;
Mengidentifikasi kondisi dan faktor utama munculnya kesadaran beragama;
Untuk menganalisis keadaan kesadaran beragama saat ini, yang memungkinkan kita mengidentifikasi ciri-cirinya dalam masyarakat saat ini.
Landasan teori dan metodologi penelitian ini adalah literatur tidak hanya dari kajian agama, tetapi juga karya-karya filsafat, sejarah, ilmu politik, dan psikologi. Yang juga banyak digunakan adalah kitab suci agama-agama utama dunia, karya para teolognya, bahan-bahan dari dewan gereja, kehidupan para orang suci, bapak gereja, pidato, dan pernyataan para pemimpin gereja saat ini. Data dari studi sosiologis tentang kesadaran keagamaan modern, yang dilakukan di wilayah yang sekarang disebut Rusia, dilibatkan secara aktif.
Analisis terhadap permasalahan teoritis kesadaran beragama yang dibahas dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan penelitian yang sistemik, berbasis nilai dan informasional, metode ilmiah umum historis dan logis, analisis dan sintesis, dll. Penulis juga berpedoman pada ketentuan dan kesimpulan tentang topik yang diteliti yang terdapat dalam karya-karya penulis dalam dan luar negeri.
Kebaruan proyek diploma yang didalamnya dilakukan analisis menyeluruh tentang kesadaran beragama adalah sebagai berikut:
Definisi konsep “kesadaran beragama” dan ciri-ciri utama kesadaran beragama terungkap;
Perubahan kesadaran keagamaan orang Rusia saat ini dianalisis.
Makna praktis dari karya ini adalah bahwa hasilnya dapat menjadi landasan teoritis dan metodologis untuk kajian lebih lanjut tentang kesadaran beragama, kajian yang lebih lengkap tentang permasalahan yang terkait dengan fenomena kesadaran beragama.
Hasil teoritis, ketentuan dan kesimpulan yang diperoleh selama penelitian dapat digunakan ketika memberikan kuliah dan menyelenggarakan seminar pada disiplin ilmu berikut: studi agama, filsafat, sosiologi, psikologi. Bahan penelitian tersebut dapat digunakan dalam pengembangan kegiatan mengkaji kesadaran beragama umat modern, serta dalam karya di kalangan generasi muda.
Elemen dan struktur agama berevolusi dan berubah sepanjang sejarah. Dalam masyarakat primitif, agama belum muncul sebagai entitas yang relatif independen. Selanjutnya, setelah menjadi wilayah kehidupan spiritual yang relatif mandiri, sekaligus menjadi semakin terdiferensiasi, unsur-unsur menonjol di dalamnya, dan hubungan antar unsur-unsur tersebut terbentuk. Dalam agama, dibedakan kesadaran keagamaan, aktivitas, hubungan, institusi dan organisasi. Kesadaran beragamalah, sebagai sebuah komponen struktural, yang akan kita bahas pada bab-bab berikutnya.
Bab 1 Kesadaran Beragama: Kemunculan, Esensi, Struktur, Ciri-ciri
Poin kunci dalam istilah “kesadaran beragama” tidak diragukan lagi adalah istilah religiusitas. Dengan demikian, “Encyclopedic Dictionary of Religion” memberikan tiga arti dari istilah “religiusitas”: 1) keterlibatan seseorang yang berlebihan dan tidak pantas dalam masalah keagamaan; 2) kesempatan bagi seseorang untuk menjalin hubungan dengan Tuhan; dan 3) keinginan manusia untuk bertindak melampaui kepentingan jasmani semata, untuk berpartisipasi dalam budaya dan masyarakat orang-orang yang berpikiran spiritual. Dalam karya peneliti Bulgaria V. Milev “Psikologi dan Psikopatologi Agama”, religiusitas didefinisikan sebagai kategori psikologis yang paling penting, terdiri dari banyak komponen, yang utamanya adalah emosional dan intelektual.
Saat ini, tidak ada definisi umum mengenai istilah “kesadaran beragama”, karena ini adalah struktur yang dinamis dan terus berubah, objektif dan subjektif, umum dan individual, ditentukan oleh evolusi gagasan kita tentang dunia, dunia. gambaran dunia dan gambaran umum dunia.
Dalam ensiklopedia psikologi besar kita menemukan definisi berikut: “Dari sudut pandang materialisme, refleksi fantastis oleh orang-orang tentang kekuatan alam dan sosial yang mendominasi mereka dalam gambaran, gagasan, gagasan yang berkorelasi dengan tindakan kekuatan supernatural. Ia memiliki akar kognitif dan emosional: ketakutan akan kekuatan alam yang tidak dapat dipahami, perasaan tidak berdaya dalam menghadapi penyakit, bencana alam, kelaparan, dll. Awalnya termasuk totemisme - kepercayaan pada kekerabatan sekelompok orang dan pelindung mereka. hewan, tumbuhan, dan fetisisme - kepercayaan pada kekuatan supernatural benda, benda, dll. Bentuk yang lebih dewasa mencakup animisme - keyakinan bahwa manusia, hewan, tumbuhan, dan bahkan benda, bersama dengan sisi indra yang terlihat, memiliki aktivitas khusus. , prinsip independen - jiwa. Keinginan untuk memahami dan menjelaskan asal usul benda, fenomena alam dan manusia itu sendiri menyebabkan munculnya gagasan-gagasan mitologis sebagai bentuk spesifik konkretisasi sensorik dari kategori-kategori abstrak. Dewa mitologis yang dipersonifikasikan dan direnungkan secara sensual telah mewujudkan prinsip-prinsip abstrak di antara para filsuf Yunani kuno pertama. Ketika masyarakat kelas berkembang, para dewa menjadi semakin mirip raja duniawi dan rekan-rekan mereka. Keyakinan agama disistematisasikan oleh para pendeta dan pendeta lain dari aliran sesat; mereka menciptakan ajaran-ajaran teologis dan, melalui organisasi mereka (gereja), berdasarkan ajaran-ajaran ini, membentuk kesadaran beragama.”
Sarjana agama Rusia I. Yablokov memberikan definisi kesadaran beragama sebagai berikut: “kesadaran beragama adalah salah satu fenomena yang paling banyak dipelajari dan pada saat yang sama jauh dari fenomena yang dapat diuraikan sepenuhnya. Basisnya adalah pengalaman hidup subjektif dari perjumpaan dengan Realitas Tertinggi dan wakil-wakilnya, perasaan akan kehadiran misteri yang tak terbatas, tatanan tak kasat mata dalam kehidupan segala sesuatu, dan manusia pada awalnya.”
Ciri dan tanda utama kesadaran beragama adalah keyakinan beragama, namun tidak semua keyakinan bersifat religius. Iman adalah keadaan keyakinan psikologis khusus terhadap sesuatu dengan informasi yang tidak memadai. Keyakinan akan kebenaran gagasan, tergantung pada kurangnya informasi yang akurat tentang ketercapaian tujuan. Berisi harapan bahwa apa yang diinginkan akan terkabul. Keadaan psikologis ini terjadi dalam situasi probabilistik ketika ada peluang untuk melakukan tindakan yang berhasil. Jika suatu peristiwa telah terjadi atau sudah jelas tidak mungkin, jika suatu tingkah laku telah dilaksanakan atau diketahui tidak akan dilaksanakan, jika terbukti benar atau salahnya suatu gagasan, maka keimanan pun luntur. .
Keyakinan agama adalah iman:
– dalam keberadaan objektif dari hal-hal gaib;
– kesempatan untuk berkomunikasi dengan hal gaib ini;
- dalam pelaksanaan sebenarnya dari beberapa peristiwa mitologis, partisipasi di dalamnya;
– dalam kebenaran representasi dogma dan teks yang sesuai;
Berhubungan dengan keimanan adalah sifat dialogis kesadaran beragama.
Dalam kesadaran beragama, dapat dibedakan dua tingkatan: biasa dan konseptual.
Pada tataran sehari-hari, kesadaran beragama hadir dalam bentuk gambaran, gagasan, sikap, suasana hati, perasaan, pengalaman, kebiasaan, dan tradisi. “Pada tingkatan ini terdapat unsur keyakinan agama yang bersifat rasional, emosional, dan kemauan, namun yang dominan peranannya terdapat pada unsur emosional-kehendak. Isi kesadaran dibalut dalam bentuk visual dan figuratif. Berdasarkan sifat pembentukannya, sebagian besar bersifat individual. Oleh karena itu, tingkatan ini sering disebut psikologi agama.”
Pada tataran konseptual, kesadaran beragama berperan sebagai seperangkat konsep, gagasan, prinsip, dan konsep yang dikembangkan secara khusus dan sistematis. Meliputi doktrin Tuhan, dunia dan manusia, penafsiran bidang-bidang utama kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip pandangan dunia keagamaan, dan filsafat agama. Isi doktrin agama dikembangkan dan dibuktikan dalam cabang khusus ilmu agama - teologi atau teologi, yang mewakili keseluruhan disiplin ilmu teoretis dan praktis: apologetika, dogmatika, teologi pastoral, dll.
Tugas pokok teologi adalah membentuk gagasan-gagasan keagamaan yang ortodoks, menafsirkan ketentuan-ketentuan pokok doktrin dalam bentuk yang ditentukan oleh kepentingan gereja sesuai dengan tuntutan zaman, dan memerangi penyimpangan-penyimpangan sesat. Paus Yohanes Paulus II menulis yang berikut tentang hal ini: “Masing-masing teolog harus menyadari apa yang Kristus sendiri katakan: “Ajaran yang kamu dengar bukanlah milikku, tetapi Dia yang mengutus Aku - Bapa” (I. hal. 14, 24).
Perwakilan pemikiran teologis berbicara tentang prioritas yang tak terbantahkan dari sisi dogmatis dan doktrinal kesadaran beragama. Pencapaian tujuan utama keyakinan agama - “persatuan dengan Tuhan”, “keselamatan jiwa”, menurut pendapat mereka, hanya mungkin atas dasar penerimaan doktrin dalam bentuk yang dirumuskan oleh gereja. Penyimpangan dari ketaatan yang ketat terhadap doktrin ini adalah bid'ah, kemurtadan dan dapat dikutuk dan dihukum.
Para pendukung studi keagamaan ilmiah menunjukkan sifat sekunder dari teks dan dokumen keagamaan. Menurut mereka, “teks-teks keagamaan tersebut merupakan hasil pengolahan, sistematisasi dan kodifikasi pengalaman keagamaan primer, yaitu gagasan, perasaan dan pengalaman yang dikembangkan umat beriman dalam proses kehidupannya. Pada saat yang sama, perlu dicatat bahwa dogma sistematis yang dikembangkan oleh para ideolog dan disetujui oleh gereja, pada gilirannya, mempunyai pengaruh yang kuat terhadap sifat kesadaran keagamaan sehari-hari, membentuknya ke arah yang diberikan oleh organisasi-organisasi keagamaan.” Jadi, dalam bentuk agama yang sudah maju, kita mungkin tidak berbicara tentang prioritas tingkat kesadaran beragama mana pun, tetapi tentang interaksi dan pengaruh timbal baliknya satu sama lain. Kesadaran beragama merupakan unsur utama agama. Semua elemen lain bergantung padanya dalam bentuk dan konten. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengidentifikasi kondisi dan faktor utama munculnya kesadaran beragama, esensi dan komponen strukturalnya.
1.1 Kondisi dan faktor munculnya kesadaran beragama
V.S. Soloviev menulis dalam karyanya bahwa untuk membangun moralitas, gagasan saja tidak cukup; sebuah “organisasi moral” juga diperlukan. Soloviev menghubungkan landasan moralitas dengan agama, sehingga memunculkan gagasan perlunya organisasi keagamaan. Dalam agama ada hubungan antara zaman dan generasi. Jika konsep agama, tulis Soloviev, diasosiasikan hanya dengan sesuatu yang telah menuju kekekalan, sebagai sesuatu yang “selesai”, maka kita menjadikan agama hanya sebagai “peninggalan”. “Di mana tradisi ditempatkan di tempat penyembah (di mana, misalnya, kebenaran tradisional dari konsep Kristus dipertahankan tanpa syarat, tetapi kehadiran Kristus sendiri dan Roh-Nya tidak dirasakan), maka kehidupan beragama menjadi tidak mungkin, dan upaya apa pun untuk membangkitkannya secara artifisial hanya akan semakin mengungkap kerugian yang fatal.” Organisasi keagamaan tidak hanya mencakup gereja, tempat umat beriman berkumpul untuk kegiatan keagamaan kolektif, tetapi juga keluarga, sekolah, seni, hubungan antaragama, dll. Kehidupan keagamaan berlangsung di bawah pengaruh banyak kondisi eksternal dan faktor internal. Inilah yang terjadi dengan kesadaran beragama.
Proses pembentukan kesadaran keagamaan masyarakat dan individu yang kompleks dan beragam terjadi dengan adanya dan aktivitas sekelompok faktor, yang dapat diklasifikasikan dengan mengacu pada oposisi logis “alami - sosial”. Kategori “alami” dan “sosial” memungkinkan kita mengidentifikasi faktor-faktor yang bersifat alamiah dan sosial di antara sekian banyak prasyarat, kondisi, sebab dan mekanisme yang terlibat dalam pembentukan unsur-unsur struktural kesadaran beragama.
Struktur faktor alam dalam pembentukan kesadaran beragama meliputi sistem alam yang terdiri dari unsur-unsur yang bersifat eksternal dan internal. Pengaruh aktif alam luar dan dalam terhadap proses munculnya kesadaran beragama merupakan salah satu wujud dari kenyataan bahwa: “alam selalu, terutama pada masa pra-peradaban, mempengaruhi masyarakat manusia, tidak hanya dari luar saja. suatu kondisi keberadaannya, tetapi juga dari dalam – sebagai prasyarat alamiah perkembangannya."
Dengan demikian, faktor alam dalam lahirnya kesadaran beragama meliputi faktor alam luar dan dalam. Inti dari faktor alam eksternal adalah bahwa mereka tidak terkena pengaruh antropogenik dan sosiogenik dari lingkungan individu. Itu. sistem alam yang membentuk kondisi lingkungan manusia yang tidak termasuk dalam proses produksi dan kegiatan ekonominya merupakan faktor alam eksternal yang mendasari strukturnya.
Sistem alam tunduk pada perkembangan hukum alam dan ada di luar dan terlepas dari kesadaran manusia. Namun sistem alam merupakan lingkungan geografis alami manusia dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap munculnya formasi sosial baru atau transformasi yang sudah ada. Kehadiran dan berfungsinya habitat alam-geografis suatu individu dan kelompok masyarakat memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam struktur faktor alam eksternal sebagai prasyarat bagi munculnya gambaran sosial-keagamaan, pengalaman, dan unsur-unsur penyusun kesadaran beragama lainnya. .
Terbentuknya komponen-komponen penyusun kesadaran beragama tergantung pada keberadaan dan aktivitas kondisi geografis keberadaan masyarakat yang bersifat obyektif. Selain premis di atas, sebagai ciri sistem alam, kondisi geografis keberadaan dan tempat tinggal individu, yang tidak dipengaruhi oleh masyarakat, tetapi mempengaruhinya, harus dianggap sebagai faktor independen yang termasuk dalam bidang alam eksternal. Alam luar, yang tidak tersentuh manusia, membentuk dasar alami keberadaan manusia. Oleh karena itu, lingkungan alamiah keberadaan dan habitat individu, beserta komponen-komponen lainnya, merupakan landasan yang menjadi landasan terbentuknya dunia kehidupan seseorang sebagai subjek sosial. Pyrin A.G. menulis bahwa konsep “lingkungan” memungkinkan, pertama, untuk menguraikan kerangka habitat manusia, dan, kedua, untuk menetapkan komponen utamanya.”
Waktu, ciri-ciri bentang alam, suara alam hidup dan mati, ciri-ciri flora dan fauna suatu wilayah tertentu memegang peranan penting dalam proses pembentukan kesadaran keagamaan masyarakat dan individu serta kekhususannya. Tanpa menimbulkan ancaman bagi kehidupan masyarakat, unsur-unsur struktural faktor alam eksternal ini, melalui pengaruhnya terhadap kesadaran individu, menempati tempat penting dalam perjalanan asal-usul dan evolusi kesadaran keagamaan individu dan masyarakat. Namun, tidak mungkin memahami dan menjelaskan proses terbentuknya kesadaran beragama hanya berdasarkan berfungsinya alam eksternal. Tidak diragukan lagi, faktor alam eksternal memegang peranan penting dalam proses kompleks pembentukan kesadaran beragama. Pengaruh mereka sangat kuat terutama pada masa pra-peradaban. Namun hanya kehadiran dan berfungsinya faktor alam internal yang mengarah pada terbentuknya sifat spesifik dari gambaran, gagasan, pengalaman, keyakinan, yang bersama-sama membentuk kesadaran keagamaan baik individu maupun kelompok masyarakat. Oleh karena itu, faktor alam internal memegang peranan dominan dalam pembentukan kesadaran beragama. Dengan kata lain, faktor alam yang bersifat internal mampu menentukan warna spesifik dari gambaran, gagasan, emosi, dan perasaan individu sebagai umat beragama. Wilayah alam batin harus mencakup faktor-faktor berikut yang membentuk kesadaran beragama: tubuh, jiwa manusia dan pola fungsinya. Semua elemen ini sangat penting bagi pembentukan kesadaran beragama baik individu maupun masyarakat. Akan tetapi, sifat batiniah yang ikut serta dalam proses pembentukan tingkat kesadaran beragama sosial dan individu tidak sejalan baik bagi masyarakat maupun bagi individu.
Tubuh manusia, ciri-ciri biotiknya, misalnya kemampuan melihat, merasakan, mempersepsi dan lain-lain, ditentukan oleh kejiwaannya. Jiwa manusia bersifat sosial dan alami: bentuk alaminya penuh dengan konten sosial. Kesatuan biotik dan jiwa manusia yang tidak dapat dipisahkan diwujudkan dalam proses pembentukan citra dan gagasan yang bersifat religius. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan kesadaran beragama, tempat penting ditempati oleh sifat-sifat dan pola-pola jiwa yang dihasilkan oleh biotik manusia, yaitu menempati wilayah alam batin. Kecenderungan mental yang terbentuk secara genetik, kemampuan jiwa untuk merespons dengan cara tertentu terhadap rangsangan eksternal, kebutuhan organik, dan lingkungan motivasi individu yang terkait, termasuk dalam alam internal dan menempati tempat tertentu dalam struktur faktor-faktor pembentukan. kesadaran beragama.
Jiwa manusia merupakan kondisi penting bagi munculnya keyakinan dan gagasan keagamaan, yang tanpanya kesadaran individu, dan oleh karena itu, kesadaran beragama, tidak mungkin muncul. Mewakili kesatuan yang kontradiktif antara alam internal dan sosial yang terinternalisasi, jiwa individu berpartisipasi dalam proses pembentukan kesadaran keagamaan publik dan individu.
Tidak diragukan lagi, kemampuan membentuk gambaran suatu objek dan gagasan tertentu tentangnya sudah ada pada manusia bahkan sebelum munculnya kesadaran beragama. Namun, berkembang selama berabad-abad atas dasar refleksi proses alam dan masyarakat dalam kesadaran umat manusia, kesadaran beragama ditentukan oleh kehadiran jiwa individu. A. I. Shaforostov menulis bahwa “urgensi masalah memahami iman sebagai refleksi juga disebabkan oleh fakta bahwa iman tidak selalu mencerminkan kenyataan.<...>iman sampai batas tertentu berhubungan dengan imajinasi dan fiksi, dan tidak ada mekanisme yang dapat diandalkan untuk memisahkan realitas dari imajinasi dalam isi iman.” Inilah kesatuan dialektis faktor alam dan sosial internal dalam lahirnya kesadaran beragama. Pembentukan gagasan, gambaran, dan perasaan yang bersifat keagamaan, yang bersama-sama membentuk kesadaran beragama, terjadi dalam kerangka bentuk kesadaran jiwa manusia yang paling berkembang. Peneliti modern mendefinisikan kesadaran sebagai “keadaan khusus kehidupan mental seseorang, yang diekspresikan dalam pengalaman subjektif dari peristiwa-peristiwa di dunia luar dan kehidupan individu itu sendiri, dalam laporan tentang peristiwa-peristiwa tersebut.”
Prasyarat munculnya kesadaran dan evolusinya terletak pada kekhasan perkembangan dan fungsi jiwa manusia. Mereka memanifestasikan dirinya baik dalam bidang alam maupun sosial. Namun kesadaran, seperti halnya jiwa manusia dengan kekhasan fungsinya, menempati wilayah kesatuan dialektis antara alam internal dan sosial. Misalnya, efek impulsif pada jiwa tidak hanya berkontribusi pada konstruksi gambaran, ide, keyakinan, dan tindakan yang bersifat tertentu, tetapi juga disertai dengan perubahan pada tingkat somatik, yaitu mengaktifkan refleksi non-figuratif. Refleksi non-figuratif, yang disebut “sensasi gelap” (menurut I.M Sechenov), juga memainkan peran tertentu dalam proses munculnya kesadaran beragama. Mengalami berbagai tingkat rasa sakit selama ritual keagamaan mengaktifkan proses pembentukan gagasan keagamaan individu. Kita harus setuju dengan G.L. Shikhov, yang mencatat bahwa "rasa sakit berkontribusi pada transisi ke "suprarealitas", membawa subjek melampaui batas fisik." Dengan demikian, sensasi dan perasaan somatik tidak mencerminkan objek di luar seseorang, tetapi mencirikan objek internal. keadaan tubuh Misalnya saja perasaan berdebar-debar saat salat dan lantunan dapat menyebabkan keadaan mengalami kehadiran alam gaib, dan perubahan pada tingkat psikosomatis dapat memberikan kontribusi pada penyembuhan penyakit tertentu.
Interaksi aktif antara alam sadar dan alam bawah sadar juga memegang peranan khusus dalam pembentukan unsur kesadaran keagamaan individu. Garis kabur antara kedua keadaan jiwa manusia ini memungkinkan terjadinya perubahan tertentu tidak hanya pada tingkat proses mental, tetapi juga pada tingkat fisiologis. Keadaan mental yang mengaktifkan proses psikosomatik yang termasuk dalam bidang tindakan alami internal secara bersamaan sebagai akibat dari manifestasi pola mental dan sebagai prasyarat untuk munculnya "pengalaman keadaan" khusus, di bawah kondisi di mana pembentukan kesadaran beragama kemungkinan besar.
Dengan demikian, landasan kodrat yang menyertai proses kompleks pembentukan kesadaran beragama harus mencakup prasyarat biopsikik dan mekanisme yang menempati wilayah kodrati internal. Sifat alami seseorang - naluri, khususnya naluri mempertahankan diri dan ketakutan yang ditimbulkannya, kebutuhan, misalnya, kebutuhan akan kesadaran akan ancaman terhadap keberadaan, karakteristik biotik seseorang, jiwanya, pola fungsinya , mekanisme mental hubungan kelompok alami, kesiapan fisiologis dan mental untuk tunduk pada pengaruh sugestif (lat. Suggestio - sugesti) dari luar dan sugesti diri merupakan syarat dan prasyarat yang diperlukan bagi pembentukan kesadaran beragama pada semua tahap perkembangan sejarah. Selain hal-hal di atas, faktor alam internal dalam pembentukan kesadaran beragama masyarakat antara lain: hubungan alamiah jenis kelamin dan usia, cara alami mengatur perilaku individu, pola hubungan kelompok alami.
Munculnya dasar-dasar kesadaran beragama dan proses pembentukannya tidak mungkin terjadi tanpa adanya aktivitas faktor alam internal. Faktor-faktor ini, tanpa berlebihan, menempati tempat khusus tidak hanya dalam landasan kesadaran keagamaan, tetapi juga seluruh proses dan fenomena sosial. Dengan kata lain, faktor alam internal merupakan suatu sistem yang kompleks, yang unsur-unsur strukturnya saling berinteraksi erat satu sama lain. Selain itu, dalam seluruh tahapan sejarah perkembangan masyarakat, faktor alam eksternal dan faktor alam internal merupakan satu landasan bagi proses pembentukan kesadaran beragama dan tidak dapat dianggap terpisah satu sama lain. Menurut Yu.V. Gavrilova, “dasar pembentukan kesadaran beragama terletak pada kesatuan dialektis tidak hanya alam eksternal dan alam internal, tetapi juga kondisi sosial, prasyarat dan mekanisme. Hal ini memungkinkan kita berbicara tentang dialektika faktor alam dan sosial dalam pembentukan kesadaran beragama.”
Perlu diketahui bahwa intensitas pengaruh alam batin terhadap proses lahirnya kesadaran beragama pada periode sejarah yang berbeda tidak sama dan dibedakan berdasarkan orisinalitasnya. Namun, meskipun alam eksternal mampu ikut serta dalam munculnya gambaran dan gagasan yang bersifat religius, yang menjadi prioritas dalam kondisi sistem komunal primitif, maka alam internal mempengaruhi pembentukan kesadaran beragama sepanjang perkembangan sejarah. masyarakat.
Alam batin masih dicirikan oleh tingkat aktivitas yang cukup tinggi dalam pembentukan unsur-unsur individu kesadaran beragama dan pelipatannya menjadi satu sistem konsep dan doktrin. Namun seiring berjalannya waktu, pengaruh faktor alam terhadap munculnya kesadaran beragama semakin melemah. Hal ini terkait dengan proses perkembangan sosial, dan akibatnya dengan subordinasi alam kepada masyarakat.
1.2 Esensi dan struktur kesadaran beragama
Pada paragraf sebelumnya telah kita identifikasi kondisi dan faktor munculnya kesadaran beragama. Sekarang kita akan mengidentifikasi secara spesifik, esensi dan komponen struktural kesadaran beragama.
Ketika kita berbicara tentang agama, mau tidak mau muncul pertanyaan tentang kekhususan kesadaran beragama, yang tidak diragukan lagi, dalam beberapa hal pasti berbeda dari kesadaran “duniawi”, dan yang dimaksud di sini bukan hanya murni psikologis, tetapi juga eksistensial. kekhususan: religiusitas sebagai faktor spiritual kehidupan seseorang tidak hanya menentukan reaksi perilakunya, kecenderungannya terhadap bentuk-bentuk kehidupan sosial tertentu atau pandangan dunianya, tetapi juga menentukan sikap nilai tertentu terhadap kehidupannya sendiri, terhadap kehidupan makhluk hidup lain dan terhadap keberadaan secara umum.
Tentu saja, faktor nilai juga berperan dalam bidang budaya manusia lainnya: tidak dapat disangkal kehadirannya dalam sains, di mana nilai tertinggi adalah kebenaran (tidak peduli bagaimana istilah ini didefinisikan, definisi serta modelnya untuk memahami dan menentukan kebenaran. ada banyak kebenaran atau kesalahan teori atau pernyataan individu), peran kuncinya dalam seni jelas, di mana ia bertindak sebagai nilai keindahan, dan terlebih lagi dalam etika.
Kesadaran beragama memiliki perbedaan yang sangat besar dengan bentuk kesadaran nilai lainnya. Namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam kesadaran beragama itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan dunia keagamaan seorang Kristen sangat berbeda dengan pandangan dunia keagamaan seorang Tao atau Budha, dan pandangan dunia Protestan berbeda dengan, misalnya, seorang Katolik atau Ortodoks. Wajar saja, pandangan dunia keagamaan juga dipengaruhi oleh tingkat filosofis agama, yang terdapat dalam setiap sistem keagamaan yang cukup berkembang. Dialah yang memberi kita kesempatan untuk membedakan antara nilai-nilai agama, moral, estetika dan dengan cara ini menyoroti kesadaran keagamaan tempat khususnya dalam budaya. Hal ini juga menjamin interaksi antara praktik keagamaan dan sikap mental itu sendiri, di satu sisi, dan komponen budaya lainnya - filsafat, etika, politik, dll - di sisi lain.
Kesadaran beragama sebagai salah satu aspek kehidupan spiritual berinteraksi dengan bentuk-bentuk kesadaran sosial dan kehidupan sosial lainnya, oleh karena itu kesadaran beragama dapat berupa berbagai macam sistem pandangan dunia filosofis yang didasarkan pada cita-cita sentral dunia – keberadaan. Tuhan.
Kesadaran beragama sebagai wujud kesadaran sosial, di satu sisi mencerminkan eksistensi sosial (eksistensi seseorang yang beragama), dan di sisi lain (keberadaan) itu sendiri yang menciptakannya. Analisis terhadap fungsi dan interaksi unsur-unsur struktur kesadaran sosial menunjukkan bahwa agama merambah ke segala bidang, mempunyai pengaruh tertentu terhadap semua unsur, menentukan hubungan dengan dunia secara keseluruhan, dengan keluarga, dengan masyarakat...
Mari kita kenali beberapa ciri dasar kesadaran beragama yang mendefinisikannya sebagai fenomena budaya:
Pertama, kesadaran beragama mengandaikan refleksi individu yang kompleks dan tingkat tinggi terhadap posisinya dalam masyarakat dan sikapnya terhadap nilai-nilai agama. Kurangnya refleksi, keimanan yang naif hampir tidak sejalan dengan kesadaran beragama, dan hal itu sendiri tidak hanya memungkinkan, bahkan secara langsung memerlukan sikap kritis terhadap konsep-konsep agama yang ada, amalan ibadah dan perintah moral yang berdasarkan teks-teks agama. Pembawa kesadaran beragama selalu berpotensi sesat atau pembangkang, hal ini sangat terlihat pada para pemikir India modern yang dimulai dengan R.M. Roy dan lawannya Dayananda, menjadikan Hinduisme tradisional mengalami revisi yang mendalam dan radikal baik dari segi pandangan dunia dan (yang jauh lebih penting dalam Hinduisme dengan prinsip ortopraksinya) dalam hal praktik sosial yang memunculkan pembagian varna yang terkenal. masyarakat India dan keberadaan fenomena neo-Vedantisme yang menjijikkan secara moral seperti ketidaktersentuhan. Hal ini bahkan dapat dilihat lebih baik lagi dalam karya-karya Teilhard de Chardin, yang pendekatannya terhadap prinsip-prinsip teologi Katolik sangat tidak konvensional sehingga gereja melarangnya untuk berbicara secara terbuka tentang pandangannya. Kesadaran beragama yang tidak ortodoksi, sikap kritis terhadap dogma-dogma yang sudah dikenal, namun menjadi insentif bagi pengembangan agama sebagai salah satu elemen kebudayaan. Kesadaran beragama adalah semacam “faktor mutagenik” dalam agama, yang dapat memunculkan bentuk-bentuk religiusitas yang tidak dapat bertahan atau benar-benar merusak, serta bentuk-bentuk religiusitas yang sangat vital dan bahkan diperlukan bagi budaya. Tentu saja, pembawa kesadaran beragama sama sekali tidak perlu menolak keadaan yang ada dalam agamanya; dia dapat menerimanya sepenuhnya, tetapi bagaimanapun juga ini bukanlah ketundukan acuh tak acuh dari seseorang yang tidak memikirkan tentangnya. posisinya di dunia dan secara tidak sadar berdamai dengan dirinya, tetapi menyadari suatu posisi, yang memilikinya, seseorang tidak lagi menjadi bahan sejarah, tetapi - setidaknya sampai batas tertentu - menjadi pemain penuh di bidang sejarah.
Dan kedua, kesadaran beragama sebagai salah satu bentuk kesadaran budaya mengandaikan, sebagai berikut, penerimaan seseorang atas tanggung jawab tidak hanya atas kedudukannya sendiri di dunia, tetapi juga atas kedudukan dunia itu sendiri. Hal ini terutama terlihat dalam ajaran Teilhard dan Aurobindo: “di mana manusia muncul tidak hanya sebagai kekuatan sosial, tetapi juga sebagai kekuatan kosmik - dan bukan manusia sebagai Homo sapiens secara keseluruhan, bukan sebagai spesies, tetapi setiap individu, tidak peduli betapa kecil dan lemahnya Religiusitas bawah sadar muncul dalam perilaku dan pemikiran seseorang sebagai penyerahan diri pada takdir atau karma, yang karenanya ia dilahirkan, misalnya, di India, bukan di Jerman, di varna Sudra, dan bukan Brahmana; seseorang di sini menerima begitu saja hal-hal yang ada, bahkan tanpa mempertanyakan keadilan atau ketidakadilan “makhluk” ini. Religiusitas yang sadar menuntut seseorang untuk menyadari dirinya sendiri, kewajibannya terhadap dirinya sendiri, masyarakat, dunia dan Tuhan dan mendorongnya untuk mengajukan tidak hanya pertanyaan-pertanyaan praktis dan sehari-hari, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan eksistensial - teologis, estetika dan moral.
Komponen struktural utama kesadaran beragama dapat dibagi:
– menurut proses pembentukannya – merupakan obyek, subyek, isi, sarana, pengelolaan;
– menurut tingkat kognisi – alam bawah sadar, kesadaran biasa, kesadaran teoretis (teologi), kesadaran super, ideologi.
Ilyin A.I. mengusulkan struktur kesadaran keagamaan yang diperluas: “tindakan keagamaan, isi keagamaan, dan subjek keagamaan.”
Di bawah tindakan keagamaan Ilyin A.I. memahami keadaan jiwa manusia yang meliputi: perasaan, imajinasi, pemikiran, kemauan, sensasi indrawi, dorongan naluri. Isinya adalah apa yang “diambil” atau “diterima” oleh jiwa beragama.” Inilah cinta kepada Tuhan, doa, rasa syukur kepada Tuhan, kutukan dosa, pujian, dogma. Subjek agama adalah Tuhan; tindakan dan konten saling berhubungan dan saling bergantung, meskipun Ilyin mengklasifikasikan tindakan dan konten ke dalam rencana dan kategori yang berbeda. Dengan demikian, tidak mungkin memisahkan suatu tindakan dari isi secara mekanis: isi diwujudkan dalam tindakan, tindakan tidak dapat dibayangkan tanpa isi, selalu diisi dengan isi. Menurut ajaran suci, perasaan, pemikiran, kemauan, dan unsur-unsur pembentuk perbuatan lainnya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Tuhan, diungkapkan dalam doa, kutukan dosa, pujian, dan tidak dapat dipisahkan dari dogma. Jika kita mengikuti prinsip-prinsip ajaran suci dengan ketat, maka tindakan memisahkan perbuatan dari isinya adalah melanggar hukum.
Jika kita memperhatikan struktur kesadaran beragama menurut proses pembentukannya, seperti yang telah kami kemukakan di atas, maka yang termasuk di sini adalah komponen struktural berikut: objek, subjek, isi, sarana kontrol.
Objek kesadaran beragama merupakan suatu bentukan yang sangat kompleks, paling sedikit terdiri dari dua komponen yang terhubung secara organik. Pertama-tama, mereka adalah orang-orang dari agama yang berbeda. Agama ditujukan bagi mereka, bagi mereka untuk mengasimilasi dogma-dogmanya. Ilyin I.A. menulis tentang ini: "Jika tidak ada manusia sebagai makhluk yang terpisah dari Tuhan, dalam arti tertentu "menentang"-Nya, maka tidak akan ada agama. Agama adalah hubungan yang hidup antara Tuhan dan bukan Tuhan, yaitu manusia. Keberbedaan. Satu Ketuhanan, tanpa manusia, akan menjadi Realitas yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dipercaya, artinya, tidak lagi menjadi sebuah objek. Seseorang tanpa Tuhan akan menjadi subjek yang ditinggalkan secara agama: ia dapat menuruti berbagai firasat, khayalan, ketakutan, takhayul, yang, sementara menghuni jiwanya, akan tetap tidak ada gunanya secara keagamaan; namun agama tidak dapat muncul.”
Komponen kedua dari objek kesadaran beragama mengikuti yang pertama: karena dasar dari keyakinan apa pun (kecuali agama Buddha) adalah Tuhan, tindakannya dalam menciptakan dunia dan manusia, maka sisi kedua dari objek kesadaran beragama adalah Tuhan, dunia yang diciptakannya, alam semesta, alam, manusia. Bukan suatu kebetulan jika mereka dianggap sebagai bukti utama keberadaan Tuhan: karena alam, dunia, alam semesta ada, berada dalam keselarasan dan koherensi mutlak, maka Tuhan juga ada.
Subjek kesadaran beragama adalah sejumlah besar pendeta dari gereja-gereja yang berbeda agama. Denominasi terbesar di Rusia adalah Gereja Ortodoks Rusia. Dari 24.563 yang didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Rusia pada 1 April 2012, organisasi keagamaan Ortodoks berjumlah 13.897, tergabung dalam 160 keuskupan. Ada 437 biara Ortodoks dan 242 lembaga keagamaan. Organisasi keagamaan Muslim berjumlah 4.319 dan Protestan - lebih dari 3.000 Menurut daftar negara, pada 1 April 2012, 221 organisasi keagamaan Buddha terdaftar di Rusia. Dari jumlah tersebut, 11 terpusat, 207 komunitas (sangha), 3 lembaga spiritual dan pendidikan. Pusat agama Buddha di Rusia adalah wilayah Buryatia, Kalmykia, Tyva, Altai, Irkutsk, Omsk, dan Chita. Di dalamnya, serta di Rusia bagian Eropa, terdapat sekitar 40 ribu pengikut aktif agama Buddha, 500 ribu etnis Buddha, dan 500 ribu penganut Buddha non-etnis. Organisasi keagamaan Yahudi jumlahnya relatif sedikit - 272 sinagoga, dipimpin oleh pendeta Yahudi dan 1 lembaga pendidikan Yahudi.
Subyek kesadaran beragama, tanpa berlebihan, memegang peranan dominan dalam pemeliharaan dan pengembangannya.
Kesadaran beragama tidak bisa berada “dalam dirinya sendiri”. Perlu distribusi, dan untuk itu kita perlu dana. Mereka beragam dan mencakup kelima indera manusia: penglihatan (kemegahan gereja, pancaran lampu, lilin); pendengaran (akatis, mazmur, doa, troparia, dll); bau (dupa, dupa); sentuhan (menyentuh salib, ikon, mencuci saat pembaptisan); rasa (terutama pada saat komuni). Kami membicarakan hal ini secara lebih rinci di paragraf pertama bab ini, tetapi sekali lagi kami akan sedikit menyentuh topik ini.
Hampir semua teolog dan filsuf telah menulis tentang peran perasaan dalam pengetahuan tentang Tuhan dan dalam pembentukan kesadaran beragama. Perasaan disertakan pada saat-saat ibadah secara bersamaan dan mempunyai dampak yang kompleks terhadap jiwa manusia. Pendeta Rusia John dari Kronstadt menulis tentang ini: “Gereja, melalui kuil dan kebaktiannya, mempengaruhi seluruh pribadi, mendidiknya sepenuhnya: itu mempengaruhi penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, rasa, imajinasi, perasaan, pikiran dan kemauannya. dengan kemegahan ikon dan seluruh kuil, dering, nyanyian paduan suara, dupa, ciuman Injil, ikon salib dan suci, prosphora, nyanyian dan pembacaan kitab suci yang merdu.”
Dan terakhir, elemen struktural terpenting dari kesadaran beragama adalah pengelolaan proses ini. Hanya sedikit orang yang secara mandiri menyadari perlunya pengetahuan agama. Kebanyakan orang tidak memikirkan Tuhan pada masa kanak-kanak. Mentor pertama dalam hal ini adalah kerabat terdekat: kebanyakan nenek, lebih jarang ibu. Ayah akan terlibat dalam proses ini jauh di kemudian hari.
Dengan munculnya negara dan semakin jelasnya hubungan antara negara dan Gereja, timbul kebutuhan akan lembaga pendidikan khusus di mana anak-anak, seiring dengan pembelajaran disiplin ilmu sekuler, akan diperkenalkan dengan prinsip-prinsip ilmu agama.
Saat ini, Gereja Ortodoks Rusia memiliki 6 akademi teologi, 51 seminari, 31 sekolah teologi. Selain itu, menurut data resmi Kementerian Kehakiman Federasi Rusia, sudah ada lebih dari 100 lembaga pendidikan agama Islam yang terdaftar di negara tersebut. Hanya di Moskow terdapat Institut Peradaban Islam, Universitas Kebudayaan Muslim, Pusat Studi Arab dan Penelitian Institut Negara-negara Asia dan Afrika di Universitas Negeri Moskow. M.V. Lomonosov.
Nah, di atas kita telah mengkaji struktur kesadaran beragama menurut proses pembentukannya. Aspek kedua dari struktur kesadaran beragama adalah tingkatannya. Ilmu pengetahuan saat ini memiliki lima di antaranya: alam bawah sadar, kehidupan sehari-hari, alam teoretis (teologi), alam bawah sadar, dan ideologi.
Tingkat bawah sadar adalah wilayah kesadaran yang tidak dikendalikan (atau hampir tidak dikendalikan) oleh otak. Ia bertindak secara spontan, tanpa disadari, seperti naluri. Seseorang bereaksi terhadap impuls dari dunia sekitarnya tanpa mencatatnya dengan jelas dalam kesadarannya. Para teologlah yang mulai mempelajari tingkat kesadaran ini jauh sebelum para filsuf. Pernyataan mereka bahwa Tuhan tidak terlihat, oleh karena itu tidak dapat diketahui, tidak dapat dipahami, tidak dapat diakses, hanya dapat muncul dalam penglihatan, mimpi kenabian, awan petir, kilatan petir, aurora, dalam merpati putih, wanita atau orang tua berjubah putih, suara, nyanyian dan gambar lainnya - ini adalah tidak hanya dongeng alegoris, mitos, perumpamaan, tetapi juga pendekatan pertama terhadap kesadaran "pra-mental", terhadap "kunci sumber" yang diketahui oleh nenek moyang primitif kita dan telah sampai kepada kita dalam bentuk petunjuk yang tidak dapat dipahami dan tidak dapat dipahami. , prediksi, takdir, hanya dapat diakses oleh segelintir orang, diberkahi dengan karunia khusus untuk mengenali dan menafsirkan sinyal-sinyal yang tidak jelas ini, mengungkapkan maknanya dan menyarankan bagaimana berperilaku dalam kaitannya dengan “indikasi” kekuatan yang lebih tinggi yang tidak diketahui ini. Orang-orang yang hidup 7-10 ribu tahun SM percaya akan keberadaan kekuatan-kekuatan ini dan orang-orang yang berbicara dalam “bahasa” mereka. Dalam puisi Homer, lakon Sophocles, Aeschylus, komedi Aristophanes, dan karya sejarawan, ditemukan gaung kepercayaan kuno, yang disebut pagan dan ditolak oleh pendukung monoteisme. Para pendeta, peramal, dan peramal sangat dihormati dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting. Herodotus dan Xenophon menjelaskan dalam tulisan mereka bahwa tidak ada satu pun keputusan penting mengenai hubungan dengan negara-negara tetangga (apakah akan memulai perang dengan mereka, atau menundanya; apakah akan menerima syarat perdamaian mereka, atau menolaknya; apakah akan terlibat dalam pertempuran dengan negara tetangga. pasukan yang mendekat, atau menghindari tabrakan; mengambil apakah akan bertahan, atau, sebaliknya, melakukan serangan; apakah akan pergi dalam satu atau beberapa kolom; apakah akan menyiapkan penyergapan, atau melemparkan semua kekuatan yang ada ke dalam pertempuran - dan banyak pertanyaan lainnya ) tidak diputuskan tanpa berkonsultasi dengan para dewa atau Pythia (peramal), yang melakukan kampanye di semua pasukan. Dalam kehidupan yang damai, para peramal juga memainkan peran penting: apakah kita akan menghadapi banjir, atau akankah air surut; pengorbanan apa dan dalam bentuk apa yang harus dipersembahkan kepada para dewa agar mereka menunjukkan belas kasihan dan kebaikan, dll. Monoteisme menghancurkan pengetahuan pada tingkat kesadaran ini. Kaum pagan menjadi sasaran penganiayaan kejam yang sama seperti yang dialami komunitas pertama Yahudi, Kristen, dan Muslim. Perjuangan melawan kaum pagan disucikan dalam kitab suci. Alquran secara langsung menyatakan: “Ikutlah, hai umat Islam, apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, hormati Dia, dan jangan menyembah berhala” (Sura 7:3). Dan petunjuknya diberikan: “Aku akan menimbulkan ketakutan di hati orang-orang yang tidak beriman. Maka penggallah kepala mereka dan potonglah seluruh jari mereka” (Sura 8:12, 13). Inilah yang mereka lakukan dalam banyak kasus. Kitab suci Yahudi dan Kristen juga memberkati penganiayaan terhadap orang-orang kafir. Hukuman apa yang Tuhan kirimkan kepada orang-orang Yahudi terhadap orang Mesir kafir dijelaskan dalam buku “Keluaran”. Tuhan menginstruksikan Musa di antara perintah-perintah-Nya: “menjadi tukang sihir membawa pada kematian” (Keluaran 22:18). Perlu diingat bahwa di Rus, orang-orang kafir dibaptis ke dalam agama baru dengan api dan pedang. Gereja Katolik mendirikan Inkuisisi, yang mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal dan jutaan orang menderita, dimutilasi, dan dipermalukan. Pengetahuan kafir dibakar dengan besi panas membara.
Namun, tingkat kesadaran bawah sadar hidup dalam diri setiap orang, apapun agama atau non-keyakinannya. Z. Freud, K. Jung dengan penelitiannya membuktikan adanya alam bawah sadar. Ilmuwan alam modern menunjukkan manifestasi alam bawah sadar secara eksperimental. Ketidaksadaran kini bukan hanya milik agama, tapi juga ilmu pengetahuan. Pengetahuan teoritis dan empiris tentang hal itu sudah digunakan dalam bidang kedokteran, psikologi, pedagogi, dan ilmu-ilmu lain serta bidang praktis.
Tingkat kesadaran berikutnya adalah tingkat kesadaran biasa. Ia muncul dan terbentuk melalui kesan sehari-hari yang diterima dari kehidupan. Kekuatannya berhubungan langsung dengan kehidupan, dengan kebutuhan mendesak yang bersifat material dan spiritual. Ia mampu menyerap ilmu pengetahuan dan membuat generalisasi terhadap berbagai persoalan mendasar kehidupan, baik alam maupun sosial. Kadang-kadang melampaui teori, lebih benar dan akurat mencerminkan esensi dari fenomena dan proses yang diamati. Sejarah telah mencatat banyak contoh yang menegaskan kesimpulan ini. Pemberontakan budak, dengan segala kehancurannya, dengan jelas menunjukkan bahwa sistem perbudakan bukanlah sistem yang paling sempurna dan ditakdirkan untuk digulingkan. Meskipun para filosof terpintar menegaskan kekekalan dan kekekalannya. Pemikir Tiongkok Meng Ke (c. 372-289 SM), misalnya, membagi seluruh penduduk Kerajaan Surgawi menjadi “pria bangsawan” (jun zi), yaitu. "mereka yang mengendalikan orang", dan "rakyat biasa" (shu ming) - "mereka yang dikendalikan": "mereka yang mengerahkan pikirannya mengendalikan orang." Mereka yang melenturkan ototnya dikendalikan oleh orang lain. Yang diperintah adalah orang-orang yang memerintah mereka. Mereka yang mengendalikan masyarakat didukung oleh mereka yang mereka kendalikan. Ini adalah keadilan umum di Kerajaan Surgawi.” Aristoteles merumuskan kesimpulan ini hampir kata demi kata. Manusia, karena alasan alamiah, terbagi menjadi makhluk penguasa dan makhluk bawahan. Dominasi melekat pada mereka yang memerintah secara alami, ketundukan pada mereka yang diperintah juga melekat pada alam. “Yang pertama, karena sifat mentalnya, mampu melihat ke depan, dan oleh karena itu, berdasarkan sifatnya, ia sudah menjadi makhluk yang berkuasa dan dominan; yang kedua, karena ia hanya mampu melaksanakan instruksi yang diterimanya dengan kekuatan fisiknya, maka ia adalah makhluk yang tunduk dan memperbudak.” Namun budak-budak yang tidak berdaya, tertindas, dan kehilangan martabat kemanusiaannya membalikkan penilaian para filsuf brilian ini. Patut diingat kembali perilaku orang-orang Kristen mula-mula yang berani, tidak kenal takut, dan tidak mementingkan diri sendiri, yang lebih memilih dicabik-cabik oleh singa daripada mengorbankan iman mereka.
“Tingkat teoritis kesadaran beragama (teologi) melekat pada lingkaran orang-orang percaya yang tercerahkan yang relatif sempit,” tulis A.I. Yakovlev. doktor ilmu filsafat. “Teologi memberikan penafsiran terhadap kitab suci, memperkuat dalil-dalilnya, menggunakan data ilmu pengetahuan kontemporer sebagai argumentasi, menarik kesimpulan dan kesimpulan, meramalkan masa depan, merestorasi sejarah agama-agamanya, menunjukkan bagaimana gagasan-gagasan dan kanon-kanon keagamaan tertentu terbentuk dan berkembang, serta berasal dari gambaran alegoris dari keseluruhan risalah teoretis, menggambarkan dan memperkenalkan makna keagamaan ke dalam ritus dan ritual gereja.” Harus diakui bahwa pemikir umat manusia yang paling cerdas terlibat dalam agama-agama dunia, yang memberikan kontribusi besar tidak hanya pada teologi, tetapi juga pada budaya. , spiritualitas, moralitas, dan sains. Pembuktian pandangan keagamaan tidak hanya melibatkan para teolog profesional, tetapi juga ilmuwan, filsuf, penyair, seniman yang beriman kepada Tuhan dan yakin yakin bahwa segala penemuan mendasar dan ciptaan cemerlang mereka adalah hasil wahyu dan inspirasi Tuhan. Teologi adalah elemen struktural alami dari kesadaran beragama: jika kesadaran sosial memiliki tingkat teoretis, maka kesadaran beragama, sebagai salah satu jenis kesadaran sosial, pasti memiliki tingkat teoretisnya sendiri.
Elemen struktural berikutnya dari kesadaran keagamaan adalah alam bawah sadar. Ini mencakup pengetahuan yang tidak dapat diakses oleh tingkat kesadaran lain, termasuk pengetahuan teoretis. Ini belum merupakan pengetahuan terbuka, tetapi memanifestasikan dirinya dalam manifestasi “ajaib” yang tidak dapat dipahami. Hal ini tidak dapat diakses oleh indra manusia biasa dan hanya dapat dirasakan oleh orang yang memiliki hipersensitivitas atau dipersenjatai dengan perangkat modern. Teolog Hindu Ishvarakrishna (c. 350-c. 425 M) berbicara tentang alam bawah sadar: “Bagi Ishvarakrishna, Samkhya adalah pengetahuan pembeda yang benar tentang unsur-unsur realitas yang sangat masuk akal, yang diungkapkan melalui inferensi dengan analogi. Jenis inferensi ini menggantikan persepsi indrawi, berpindah dari dunia akibat yang dirasakan ke penyebab yang tidak terlihat, dan oleh karena itu merupakan pengetahuan sejati tentang dunia yang sangat masuk akal. Alam yang supersensible sama nyatanya dengan dunia yang dirasakan.” Pendeta Pavel Florensky juga berbicara tentang dunia realitas yang sangat peka, yang hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki kepekaan super. Ia mengemukakan adanya pneumatosfer di biosfer atau di biosfer yang merupakan pembawa seluruh budaya dan spiritualitas umat manusia.
Unsur kesadaran beragama lainnya adalah ideologi agama. Hal ini harus dipahami sebagai seperangkat teori, konsep, gagasan agama yang berkontribusi terhadap penguatan kelompok sosial dominan atau berkontribusi pada penaklukan posisi dominan oleh kelompok sosial lain dalam masyarakat atau negara. Seluruh sejarah agama merupakan perebutan posisi dominan di benak masyarakat dan menjamin posisi dominan dalam masyarakat bagi kelompok sosial tertentu. Ideologi agama dekat dengan teologi, tetapi tidak menyatu dengannya, karena inti ideologi selalu kepentingan golongan yang sedang berjuang (naik dan turun). Setiap agama di dunia dan pengakuan yang kurang lebih besar di dalamnya memiliki ideologi yang sesuai: Kristen (Katolik, Ortodoks, Protestan), Islam (Sunni, Syiah), Budha, Yahudi.
Ideologi agama adalah bagian kesadaran beragama yang paling mobile dan mudah berubah. Dia mengakui legitimasi dan independensi ilmu pengetahuan dan menggunakan pencapaiannya untuk tujuannya sendiri; menghentikan penganiayaan terhadap paganisme, menyesuaikan hari raya pagan dengan hari liburnya, “mengenakan” mereka dengan “pakaian” keagamaan yang sesuai. Dari penolakan pihak berwenang, ideologi agama dengan cepat beralih ke postulat bahwa “semua kekuasaan berasal dari Tuhan.” Namun, ideologi agama tidak menyimpang dari postulat fundamentalnya – keberadaan Tuhan, penciptaan dunia dan manusia oleh Tuhan, ketundukan tindakan manusia pada kehendak Tuhan, keberdosaan manusia dan dunia, dll.
Seperti yang Anda lihat, kesadaran beragama memiliki struktur internal yang agak kompleks. Pengetahuannya menjadikan agama sebagai komponen utama kehidupan spiritual, budaya, dan moral.
Bab 2 Ciri-ciri penting kesadaran keagamaan umat beriman di Rusia modern
Perlu diketahui bahwa saat ini kedudukan agama sedang menguat, hal ini disebabkan adanya pengaruh tertentu lembaga keagamaan terhadap kehidupan masyarakat. Dan pada saat yang sama, kecenderungan khusus dalam perkembangan kesadaran beragama mulai terlihat.
Pertama, banyak ilmuwan, termasuk M.P. Mchedlov, mencatat bahwa pada tahun 2000-an terdapat tren yang terus berlanjut menuju “peremajaan” religiusitas di Rusia: proporsi anak muda yang mendefinisikan orientasi ideologis mereka sebagai “yang beriman kepada Tuhan” melebihi kelompok umur lainnya.
Kedua, berbicara tentang hakikat religiusitas, perlu dicatat bahwa di bawah pengaruh situasi yang berubah, muncul kategori orang-orang yang “mendaftarkan” dirinya pada agama di bawah pengaruh mode publik. Kualitas religiusitas juga termanifestasi dalam fenomena spesifik ketika agama dipahami bukan dalam arti “religius”, melainkan dalam arti sosial-utilitarian, sebagai sarana menjaga budaya dan moralitas. Sangat mengapresiasi ciri-ciri ajaran agama ini, banyak pemeluk agama yang fokus pada fakta bahwa agama bermanfaat bagi masyarakat, untuk menjaga moralitas, yang lebih menunjukkan komitmen mereka terhadap gagasan humanisme daripada keimanan yang nyata, tulus dan mendalam. Proses “individualisasi” keimanan terjadi ketika masyarakat, yang menganut satu keyakinan dan dengan tulus membagikan ketentuan-ketentuan pokoknya, menyesuaikannya dengan pandangan pribadinya terhadap realitas di sekitarnya. Hasilnya adalah ada orang yang sangat mementingkan agama tertentu, ada pula yang mementingkan agama lain; Beberapa orang cenderung merayakan hari libur tertentu dan menjalankan ritual, sementara yang lain menyisihkan tanggal lain untuk diri mereka sendiri dan menganggap penting ritual lainnya. Tampaknya bagi kita bahwa situasi saat ini paling tepat dicerminkan oleh V. M. Rozin, yang percaya: orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai orang beriman datang ke gereja atau beriman karena mereka menemukan dalam agama apa yang kurang dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dengan kata lain, saat ini iman semakin menjadi salah satu jenis sosialitas.
Ketiga, para peneliti sampai pada kesimpulan bahwa menganut agama apa pun di Rusia modern adalah tanda etnis, bukan agama.
Keempat, tren lain saat ini diamati di Rusia: seiring dengan intensifikasi aktivitas agama tradisional Rusia - Ortodoksi, Islam, Budha, dan Yudaisme - bentuk-bentuk baru kehidupan keagamaan dan spiritual mulai bermunculan. I. Ya.Kanterov menyebut menurunnya popularitas agama-agama historis, di mana peran umat awam direduksi menjadi partisipasi pasif dalam ibadah dan pelaksanaan ritual, sebagai alasan munculnya dan penyebaran gerakan keagamaan baru.
Kelima, seiring dengan religiusitas tradisional, apa yang disebut pseudo-religiusitas semakin meluas, yang diekspresikan dalam fenomena sinkretisme agama - kombinasi iman kepada Tuhan dengan kepercayaan pada pertanda, UFO, sihir dan sihir, yang memikat hati orang-orang yang beriman dan tidak. -orang percaya. Kami akan membahas apa yang disebut “kebangkitan kembali” kesadaran beragama, dan religiusitas semu, sebagai cirinya, dalam dua paragraf berikutnya.
2.1 “Kebangkitan” kesadaran beragama di Rusia
Tahap baru yang mendasar dalam sejarah Rusia adalah “kebangkitan” agama yang terjadi pada akhir abad ke-20. . Salah satu faktor penting dalam pembangunan sosial adalah penguatan posisi agama, termasuk peningkatan pengaruh sosial-politik lembaga-lembaga keagamaan, yang sebelumnya terdegradasi ke pinggiran kehidupan masyarakat. Faktor agama terutama terlihat pada masa transisi pembangunan sosial, dalam situasi konflik yang pasti muncul. S. Huntington menulis bahwa: “akhir abad kedua puluh. menyaksikan kebangkitan agama secara luas, yang diwujudkan dalam menguatnya kesadaran beragama.” Menurutnya, kebangkitan agama, pertama, disebabkan oleh krisis identitas akibat perubahan sosial masyarakat modern, dan kedua, merupakan reaksi terhadap ateisme, relativisme moral, dan pemanjaan diri, penegasan nilai-nilai ketertiban, disiplin. , buruh, gotong royong dan solidaritas kemanusiaan.
Dalam kamus “Religions of the Peoples of Modern Russia”, istilah “kebangkitan agama” diartikan sebagai berikut: “suatu proses politik, hukum dan sosial budaya pada tahun 1990-an yang terkait dengan pemulihan budaya keagamaan, kebebasan hati nurani, legalisasi dan pertumbuhan aktivitas sosial organisasi keagamaan dan penganutnya. Titik awal dari proses ini adalah pertemuan Sekretaris Jenderal Komite Sentral CPSU M.S. Gorbachev dengan anggota Sinode Gereja Ortodoks Rusia (ROC) pada tanggal 30 April 1988, ketika kepala negara tidak hanya mengakui hak penuh umat beriman, tetapi juga mengundang gereja untuk bekerja sama dengan negara di bidang moral. Setelah itu, pemindahan dan pembukaan gereja-gereja yang sebelumnya diambil alih oleh negara dimulai, dan para pendeta menjadi objek perhatian media yang positif. Pada tahun 1989, Patriark dan dua metropolitan Gereja Ortodoks Rusia dari wilayah Rusia terpilih sebagai wakil rakyat Soviet Tertinggi Uni Soviet. Pada tahun 1990, lima pendeta (empat Ortodoks: Uskup Agung Platon (Udovenko), pendeta V. Polosin, G. Yakunin, A. Zlobin dan Lama Buddha E. Tsybikzhapov) dan sejumlah umat beriman dipilih secara demokratis sebagai wakil rakyat Soviet Tertinggi. RSFSR. Semuanya termasuk dalam kepemimpinan Komite Dewan Tertinggi RSFSR untuk Kebebasan Hati Nurani (ketua V. Polosin).”
Di Rusia, dalam beberapa tahun terakhir, sejak akhir tahun 80-an, babak baru dalam hubungan negara-gereja telah dimulai. Sebagai hasil dari Undang-Undang Seluruh Serikat “Tentang Kebebasan Hati Nurani dan Organisasi Keagamaan” dan Undang-Undang Seluruh Rusia “Tentang Kebebasan Beragama” yang diadopsi pada musim panas dan musim gugur tahun 1990, tindakan legislatif dan peraturan dari undang-undang yang sudah ketinggalan zaman pada tahun 1929 tentang aliran sesat, yang memuat berbagai pembatasan kegiatan organisasi keagamaan, dicabut. Banyak peluang terbuka bagi gereja untuk mempromosikan agama, berpartisipasi dalam kehidupan publik Rusia dan pelayanan sosial.
Saat ini, terjadi kebangkitan aktif lembaga-lembaga keagamaan di Rusia, yang tercermin dalam pertumbuhan masyarakat dan denominasi keagamaan. Pada tanggal 1 Januari 1994, lebih dari 11 ribu perkumpulan keagamaan telah terdaftar di Kementerian Kehakiman dan menerima hak berbadan hukum. Lima ribu komunitas agama lebih memilih beroperasi tanpa registrasi.
Pada akhir Oktober 1993, Gereja Ortodoks Rusia (ROC) memiliki 14.113 paroki, lebih dari 5 ribu di antaranya berada di Rusia. Pada tahun 1986, ada 6.745 biara di seluruh Uni Soviet, pada tahun 1986 Gereja Ortodoks Rusia memiliki 18 biara, pada tahun 1993 sudah memiliki 213 biara (langsung di Rusia - 149).
Jumlah komunitas Muslim yang terdaftar terus bertambah. Selama periode 1986 hingga 1991, jumlah mereka meningkat dari 394 menjadi 1602.
Gereja Lutheran juga memulai kebangkitannya di Rusia. Jumlah masyarakat Katolik bertambah. Situasi yang sama terjadi pada agama Buddha, jika pada tahun 1985 ada dua komunitas Buddha di Uni Soviet, sekarang, seperti yang kami sebutkan di atas, ada 207 komunitas. Asosiasi Protestan baru bermunculan di Rusia (misalnya, Mormon, Bala Keselamatan, dll.), serta berbagai agama non-tradisional (Hare Krishnas, Moonies, Baha'is, dll.)
Kebangkitan institusional denominasi agama di Rusia disertai dengan perubahan kualitatif dalam peran dan tempatnya dalam kehidupan sosial-politik dan spiritual masyarakat Rusia. Saat ini, denominasi agama telah memperoleh akses terhadap media dan mempunyai majalah dan stasiun radio sendiri. Tingkat pengaruhnya terhadap populasi meningkat. Stereotip yang terkait dengan persepsi agama sebagai “peninggalan masa lalu” di luar lingkup moralitas dan budaya kini sudah ketinggalan zaman. Agama dianggap oleh banyak orang sebagai bagian dari warisan spiritual nasional, budaya spiritual nasional, sebagai fenomena sosio-historis yang memiliki signifikansi ideologis, moral dan budaya yang cukup besar, sebagai faktor yang berperan penting dalam pembentukan kesadaran diri bangsa.
Beberapa perwakilan kaum intelektual - penulis dan penyair terkenal, ilmuwan dan seniman, yang secara terbuka mengungkapkan simpati mereka terhadap Gereja Kristen - juga memberikan kontribusinya dalam memperkenalkan agama kepada masyarakat. Orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan khusus tentang sejarah dan peran sosial agama mudah dipengaruhi oleh tokoh-tokoh populer yang berpikiran religius dalam sains dan seni. Namun hipnotis otoritas nama-nama besar berhasil. Dan tidak hanya untuk masyarakat dengan pendidikan menengah, tetapi juga pendidikan tinggi, calon dan doktor ilmu pengetahuan. Alasan yang sama menjelaskan kepercayaan beberapa ilmuwan terkenal dunia kepada Tuhan - Planck, Heisenberg, Einstein, Charles Darwin dan lain-lain. Mereka tahu betul, bahkan lebih baik dari siapa pun, spesialisasi itu, kesuksesan yang membuat mereka terkenal. Namun mereka hampir tidak tahu apa-apa atau hanya tahu sedikit sekali bidang ilmu pengetahuan lain, termasuk studi agama (sejarah dan kondisi terkini ajaran agama dan organisasi keagamaan).
Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi peningkatan minat masyarakat terhadap berbagai agama, budaya keagamaan, dan kehidupan organisasi keagamaan.
Jumlah orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai penganut suatu agama, yang percaya pada Tuhan dan hal-hal gaib secara umum, juga meningkat. Jika pada tahun 60-70an sekitar 10% penduduk dewasa menganggap diri mereka beriman aktif, maka pada tahun 1993-1994. Menurut penelitian sosiologi, jumlah orang yang menganggap dirinya beriman kepada Tuhan telah meningkat menjadi 40-50% atau lebih. Jumlah pemeluk agama di kalangan generasi muda dan intelektual meningkat.
Anda dapat mengevaluasi data yang diperoleh dengan berbagai cara. Namun tidak diragukan lagi bahwa terdapat peningkatan religiusitas dalam bentuk yang unik, yang mencerminkan perubahan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, ideologi, dan spiritual yang terjadi di Rusia setelah Agustus 1991. Krisis ekonomi dan politik yang mendalam, a penurunan tajam dalam standar hidup sebagian besar penduduk Rusia, ketidakpastian tentang masa depan, pengangguran, ketidakamanan dan stratifikasi sosial, hilangnya cita-cita spiritual dan moral sebelumnya - semua ini berdampak besar pada kesadaran masyarakat, sehingga menimbulkan keinginan akan penghiburan agama, mistisisme, dan hal-hal gaib. Sebuah “religiusitas baru” sedang muncul. Metropolitan Kirill dari Smolensk dan Kaliningrad, menilai proses yang terjadi di lingkungan keagamaan, menulis bahwa kebangkitan Ortodoksi bukanlah kebangkitan gereja dan biara, melainkan “kebangkitan agama masyarakat, “gereja” mereka, itu penerimaan secara sadar terhadap cita-cita moral injili, posisinya sebagai landasan kehidupan pribadi, keluarga, dan sosial.”
Studi sosiologis yang dilakukan di Institut Masalah Sosial dan Nasional Independen Rusia pada tahun 1993 menunjukkan bahwa dari jumlah total orang yang menyebut dirinya beriman, hanya 3% yang mengunjungi kuil (masjid, gereja, dll) setiap hari, setidaknya 3- x seminggu sekali - 9%, seminggu sekali - 26%. 51% mengunjungi kuil “sesekali”, dan 30% tidak mengunjungi sama sekali. Situasi serupa terjadi dalam pelaksanaan ritual keagamaan: di antara umat beriman, hanya 34% yang rutin melakukan ritual. Yang paling aktif dalam indikator ini adalah umat Katolik (75%), Islam dan Budha. Sedangkan bagi umat Ortodoks, di antara mereka hanya 11% yang rutin melakukan ritual, 59% hanya melakukan sebagian, dan 25% tidak melaksanakannya sama sekali. Menurut VTsIOM, pada bulan Agustus 1994, 47% orang percaya yang disurvei hampir tidak pernah menghadiri gereja, 20% melakukannya beberapa kali dalam setahun, 18% kira-kira setahun sekali, dan 2% setidaknya sekali seminggu. Data serupa diperoleh oleh VTsIOM sebagai hasil survei yang relatif baru terhadap 3.000 responden.
Hanya sisi eksternal dari keberadaan keagamaan yang dihidupkan kembali, dan bukan keimanan. Rusia sebagian besar masih merupakan negara sekuler. Masyarakat Rusia secara keseluruhan belum siap menerima nilai-nilai agama. Oleh karena itu, kita sampai pada kesimpulan berikut bahwa “kebangkitan agama” yang terjadi saat ini bukanlah sebuah kembalinya agama atau balas dendam, namun sebuah kualitas baru. Dan kualitas baru ini dapat diidentifikasi, dijelaskan, dan dianalisis hanya melalui upaya khusus, khusus, dan profesional. Apa yang dibutuhkan di sini adalah perangkat baru yang memadai dan pendekatan terpadu yang mengecualikan standar Modernitas apa pun, yang mereduksi agama dan masyarakat (budaya, politik, dll.) ke dalam landasan di luarnya.
Seperti yang kami sebutkan di atas, saat ini terdapat penerimaan terhadap religiusitas semu, yang diekspresikan dalam fenomena sinkretisme agama - kombinasi iman kepada Tuhan dengan kepercayaan pada pertanda, UFO, ilmu sihir dan ilmu gaib, yang memikat hati orang-orang yang beriman dan tidak beriman. Kami akan mendeskripsikan “religiusitas baru” ini secara lebih rinci di paragraf berikutnya, “Religiusitas semu sebagai ciri kesadaran beragama umat modern.”
2.2 Religiusitas semu sebagai ciri kesadaran beragama umat modern
Seperti yang kami catat di paragraf 2.1. “Kebangkitan” kesadaran beragama di Rusia”, muncul tren baru dalam perkembangan kesadaran beragama, yang disebut “religiusitas semu”. Dalam dekade terakhir, para sosiolog telah mengidentifikasi sekelompok kontradiksi khusus dalam masyarakat Rusia, yang mereka kaitkan dengan “sifat paradoks dari kesadaran publik.” Menurut kami, tidak ada paradoks di sini, karena kesadaran massa seringkali menciptakan bentuk-bentuk konstruksi dunia yang spesifik. Di antara yang terakhir, tempat penting ditempati oleh "delusi" - praktik magis, termasuk segala jenis penipuan massal dan tipuan.
Munculnya pasar layanan “ajaib” di Rusia dimulai dari acara televisi A. Chumak dan A. Kashpirovsky di akhir tahun delapan puluhan. Patut dicatat bahwa negara tidak menganggap perlu untuk mengendalikan dampak seperti itu terhadap kesadaran publik, sehingga meninggalkan sikap ideologis tahun-tahun sebelumnya yang ditujukan terhadap paranormal dan penyihir di bidang kedokteran. Pertunjukan A. Chumak, di mana air, krim, dan salep diduga mengandung energi ajaibnya, menyebabkan banyak "sesi kesehatan" dari berbagai dukun dan tabib.
Ada cukup banyak orang yang melakukan praktik magis, begitu pula jangkauan layanan yang diberikan. Ini semua jenis mantra cinta dan kerah, penghapusan/induksi kerusakan, berbagai konspirasi, ramalan, komunikasi dengan orang mati, layanan psikis, dll.
Semua ini baru mungkin terjadi di Rusia sekarang, ketika ateisme resmi negara telah digantikan oleh religiusitas tradisional dan religiusitas semu masyarakat. Ternyata orang Rusia yang modern dan berpikiran rasional hidup di dunia magis. Paradoks kesadaran sosial yang nyata ini juga dicatat oleh L. Ionin. Menurutnya, kemenangan pandangan dunia liberal-demokratis dan rasionalistik hanyalah fiksi belaka. Faktanya, semakin jauh kemajuannya, semakin besar skala yang memunculkan pandangan dunia magis dan dengan sendirinya berubah menjadi fenomena magis.
Mari kita beri contoh anotasi buku karya Eroshenkov M.G., Balaev V.V. “Pengantar Sihir Modern”: “Buku ini lahir sebagai hasil kolaborasi penyihir - Tyrone, yang termasuk dalam Lingkaran Penyihir Sekolah Mistik Tinggi Tibet, dan ilmuwan - Eroshenkov M.G., Doktor Ilmu Teknik, kepala laboratorium sinergi Pusat Ilmu Kedokteran Universitas Negeri Moskow mereka. M.V.Lomonosov. Dalam proses pertumbuhan spiritual dan pencarian Jalannya sendiri, seorang ilmuwan, yang menjadi akrab dengan sihir, harus memulai dari awal, dari langkah pertama yang pemalu. Hanya dengan cara inilah konsep ilmiah dapat digunakan dalam struktur pengetahuan spiritual. Jalan seorang siswa menuju ilmuwan modern ditunjukkan dalam contoh hidup salah satu penulis, atas nama siapa kisah tersebut diceritakan. Buku ini membuka rangkaian mata kuliah pengantar teori dan praktik sihir modern, yang ditandai dengan kesinambungan kerjasama dengan Guru, kedinamisan bentuk dan konsep, serta aktivitas kreativitas pribadi. Tujuan dari seri ini adalah untuk menegaskan pemahaman tentang sihir tidak hanya sebagai dasar ritual dan konspirasi kuno, tetapi juga sebagai inti ilmu pengetahuan dan pandangan dunia masa depan, ketika pembagian yang sekarang diterima antara dunia internal dan eksternal, kesadaran dan materi, pikiran dan tindakan lenyap. Untuk pertama kalinya dalam bidang sastra, aktivitas kreatif dan konsep Liga Pemimpin dan Guru Keabadian disorot.”
Dalam buku ini kita juga dapat menemukan definisi penulis tentang sihir: “Menurut saya, sihir adalah aktivitas praktis yang didasarkan pada ketidakterbatasan. Definisi seperti itu mencakup mistisisme sebagai persepsi indrawi tentang Ketakterhinggaan"; “Sihir lebih dari apa pun yang dapat dibayangkan oleh pikiran manusia, karena sihir mencakup segala sesuatu yang berada di luar jangkauan pikiran manusia. Bagi sebagian orang, ini adalah keajaiban, bagi yang lain, ini adalah pemahaman mendalam tentang "aku" seseorang, bagi yang lain, ini adalah identifikasi pola rahasia hubungan sebab-akibat Universal, bagi yang lain, ini adalah sesuatu yang lain, tetapi sihir mencakup yang pertama, dan yang kedua, dan yang ketiga, dan yang keempat, dan ada juga variasi tak terhingga dari apa yang ada di luar dunia pemahaman manusia dan pandangan intuitif ke depan. Sihir memasukkan manusia sebagai kasus khusus dari Keabadian, karena Sihir adalah milik Keabadian, dan Keabadian menampakkan dirinya melalui Sihir.” Karya ini juga menyajikan perbedaan utama antara sihir modern dan sihir kuno. Menarik, bukan?
Berikut anotasi lain dari “Buku Penyihir”: “Buku Penyihir berisi ritual, mantra, dan jimat untuk semua kesempatan. Dengan bantuan buku ini, Anda akan mampu memecahkan banyak masalah kompleks, muncul sebagai pemenang dari situasi sulit, menerima keuntungan materi, melindungi diri sendiri dan orang yang Anda cintai dari agresi fisik dan magis, menyingkirkan pengaruh berbahaya, dan mencapai cinta dan kasih sayang. menghormati orang lain.”
Sangat penting untuk memperhatikan sikap terhadap praktik magis pemuda modern. M. Mchedlova memberikan data berikut: “Institut Masalah Sosial dan Nasional Independen Rusia pada bulan November-Desember 1997 melakukan studi sosiologi nasional mengenai, antara lain, religiusitas pemuda Rusia. Dengan menggunakan metode wawancara formal, 1974 orang berusia 17 sampai 26 tahun diwawancarai. Survei ini dilakukan di 12 wilayah ekonomi teritorial Federasi Rusia (menurut zonasi Layanan Sipil Negara Rusia), serta di Moskow dan St. Petersburg, sesuai dengan kuota seluruh Rusia berdasarkan jenis kelamin, usia, komposisi nasional-etnis dan afiliasi sosial-profesional. Studi tersebut mengungkapkan tidak adanya stereotip negatif di kalangan generasi muda yang sebelumnya ditanamkan oleh program sekolah dan pendidikan ateis secara umum, seperti “agama mengganggu perkembangan ilmu pengetahuan”, “agama adalah milik perempuan tua”, dll.”
M. Mchedlov juga mencatat bahwa jika 10-15 tahun yang lalu di antara semua kelompok umur indikator religiusitas terendah (1-2%) ada di kalangan anak muda, kini perbedaan usia tidak lagi menjadi hal yang penting. Hal ini terlihat dari tanggapan responden dari seluruh kelompok ideologi. Jadi, 32,1% anak muda percaya kepada Tuhan, dan 34,9% orang dewasa; mereka yang bimbang antara beriman dan tidak beriman masing-masing - 27% dan 27,6%; mereka yang acuh tak acuh terhadap agama - 13,9% dan 14,7%; tidak beriman - 14,6% dan 13,5%. Perbedaan nyata hanya terjadi di antara mereka yang percaya pada kekuatan supernatural: 12,4% remaja dan 9,3% orang dewasa. Penulis mengemukakan bahwa kesenjangan tersebut terkait dengan ketertarikan generasi muda terhadap berbagai bentuk religiositas non-tradisional, termasuk mistisisme non-denominasi, yang meliputi kepercayaan akan komunikasi dengan makhluk halus, ilmu gaib, santet, ramalan nasib, santet, dan astrologi. .
Indikator lain diberikan oleh survei L. Novikova, yang menunjukkan peningkatan tidak begitu banyak dalam religiusitas melainkan dalam “religiusitas semu”: sebagian besar orang yang beriman kepada Tuhan tidak mematuhi persyaratan tradisional disiplin gereja, dan perilaku mereka tidak religius. dilembagakan. Penulis menjelaskan fenomena ini dengan fakta bahwa peralihan ke agama terjadi dalam situasi di mana beberapa generasi masyarakat sebagian besar tidak memiliki keterkaitan dengan institusi gereja. Religiusitas masa kini, menurut L. Novikova, memanifestasikan dirinya bukan dalam bentuk kembalinya keyakinan ortodoks, melainkan dalam bentuk pencarian spiritual spontan individu di bidang tersebut. Salah satu indikator kesadaran “religius semu” tersebut adalah jawaban yang disertakan dalam kuesioner: “Saya tidak percaya pada Tuhan, tetapi pada kekuatan supernatural.” Biasanya, dalam hal ini kita berbicara tentang mitologi parascientific (UFO, astrologi, dll.) dan parareligius (sihir, ramalan, kerusakan, dll.). Mitos semacam ini tidak memiliki karakter ideologis yang menonjol, dan sikap masyarakat terhadapnya relatif bebas. Bagi para responden, ini lebih merupakan permainan intelektual. Mungkin berpaling kepada mereka adalah bentuk utama sekularisasi kesadaran. Terdapat 6,8% responden yang bertipe ini.
Sejak awal tahun 1990-an, Rusia mengalami lonjakan pesat dalam pengobatan magis. Pasar untuk “layanan magis” terbentuk, di satu sisi, karena tingginya permintaan akan layanan tersebut, yang secara spontan muncul di Rusia karena hilangnya ideologi resmi, dan, di sisi lain, karena sangat menarik dan menjanjikan. tawaran pesulap dan tabib baru, didistribusikan melalui media massa. Sejarah kemunculan dan struktur sosial suatu organisasi sosial yang berhubungan langsung dengan sihir sangatlah indikatif.
Pada tahun 1990, sebuah organisasi publik dibentuk di Rusia, yang disebut Persaudaraan Magis Rusia (ROMB). ROMB secara resmi terdaftar di Moskow sebagai cabang dari Persaudaraan Penyihir Internasional - Lingkaran Sihir Rusia N 288 (Persaudaraan Penyihir Internasional, Cincin Rusia 288). Penciptaannya diprakarsai oleh Presiden Persaudaraan Penyihir Internasional Anthony Shelley (Inggris). Di luar negeri, organisasi publik ini terutama menyatukan pesulap panggung dan ilusionis, seperti David Copperfield. Tapi di negara kami semua orang diterima di dalamnya. Selama empat tahun pertama keberadaan organisasi, lima cabang regional dibuka: Smolensk, Vorkuta, Kemerovo, Penza dan Saratov. Pada tahun 1994, 1025 orang terdaftar di ROMB, dan pada tahun 1996 - 1340. Tentu saja, ketentuan piagam, yang membuat bergabung dengan ROMB menjadi sangat sederhana (hanya diperlukan rekomendasi dari dua anggotanya), membuat organisasi ini cukup luas.
Tujuan utama pembentukan ROMB, yang dicanangkan dalam piagamnya, adalah pengembangan menyeluruh ilmu sihir sebagai sintesis ilmu pengetahuan dan budaya, karya pendidikan, pengujian dan pemeriksaan fenomena paranormal. ROMB mengadakan dua kongres - pada tahun 1991 dan 1993. Setiap orang yang bergabung dengan Persaudaraan Sihir Rusia mengisi kuesioner di mana mereka menjawab sejumlah pertanyaan dalam bentuk bebas. Analisis kuesioner mengungkapkan dinamika perubahan komposisi kuantitatif organisasi, komposisi sosialnya, tingkat pendidikan dan usia anggotanya, arah magis yang menarik mereka yang bergabung dengan Ikhwanul, motif beralih ke praktik magis dan tingkat kemahiran. dalam teknologi ajaib calon anggota ROMB. 54% anggota ROMB adalah perempuan dan 46% adalah laki-laki. 96% wanita yang masuk ingin mempelajari dasar-dasar sihir penyembuhan dan hanya 4% yang ingin mempelajari dasar-dasar ilusionisme. Di antara pria, tren sebaliknya diamati: 84% kandidat ingin mempelajari ilusionisme dan hanya 16% yang ingin mempelajari sihir penyembuhan. Rata-rata usia wanita yang ingin mempelajari dasar-dasar ilmu sihir penyembuhan adalah 42 tahun, pria - 45 tahun. 7% anggota ROMB memiliki pendidikan tinggi (teknis - 4,5%, kemanusiaan - 2,5%), teknik menengah dan menengah - 84%, belajar di sekolah dan sekolah teknik - 9%. 11% kandidat mengidentifikasi diri mereka sebagai profesional di bidang sihir penyembuhan, memiliki metode pengobatan sendiri; banyak yang menyatakan bahwa mereka sendiri memiliki kemampuan psikis. 83% kandidat menganggap diri mereka beriman, tetapi tidak menyebutkan denominasi agama mana yang mereka ikuti. Pada tahun 1998, kontradiksi internal muncul di Persaudaraan Sihir Rusia antara anggota organisasi yang percaya pada sihir dan mereka yang menolak kekuatan supernatural. Jelas sekali, kontradiksi inilah yang menyebabkan likuidasi mandiri ROMB pada tahun 2001. Pada saat yang sama, majalah organisasi publik ini tidak lagi diterbitkan.
Mengenai situasi saat ini, saya melakukan survei terhadap generasi muda (18-25 tahun). Sebanyak 41 orang mengikuti survei tersebut. Dengan demikian, 36,6% generasi muda percaya kepada Tuhan, 26,8% ragu-ragu antara beriman dan tidak percaya; tidak beriman - 9,8%; dan yang percaya Tuhan, tapi tertarik dengan berbagai hoax ternyata 26,8%.
Untuk pertanyaan “mengapa mereka percaya pada horoskop, sihir, dll?” Lebih dari setengahnya menjawab bahwa sumber utama pendidikan mereka adalah media. Dari sinilah ketertarikan mereka berasal. Perlu diketahui bahwa media memang berperan besar dalam membentuk kesadaran religiusitas semu seseorang. Yuri Ryzhkov mendefinisikan fenomena ini sebagai “ini adalah jenis religiusitas yang secara kualitatif baru (yaitu, sangat berbeda dari agama-agama yang sudah mapan secara historis yang tradisional untuk masyarakat tertentu), yang merupakan karakteristik dari tahap perkembangan budaya modern.”
Kultus massal (quasi-) religiusitas semacam ini, karena tidak memiliki organisasi kelembagaan yang jelas, telah larut dalam ruang informasi. Karena sifatnya yang simulatif, ia menghindari formalisasi, karena efeknya sangat afektif, hampir seketika. Ia “tidak tinggal” sebagai suatu sistem pengetahuan yang jelas, melainkan beredar dalam bentuk yang acak dan tidak terstruktur. Ini adalah longsoran ramalan astrologi, simbol dan komentar esoteris, takhayul, dan sebagainya.
Orang-orang adalah konsumen tetap pasar jasa magis. Pendiri dan presiden Club of Rome, Aurelio Peccei, dalam bukunya “Human Qualities” menulis: “Inti dari masalah yang dihadapi umat manusia pada tahap evolusi saat ini adalah bahwa manusia tidak punya waktu untuk menyesuaikan budaya mereka. sesuai dengan perubahan yang mereka bawa ke dunia ini, dan sumber krisis ini terletak di dalam, dan bukan di luar, manusia. Dan solusi terhadap semua masalah ini harus datang, pertama-tama, dengan mengubah seseorang, esensi batinnya.”
Meluasnya penyebaran sihir dan ilmu gaib di masyarakat kita merupakan salah satu masalah serius. Surat kabar dan majalah okultisme diterbitkan dalam sirkulasi massal, toko “khusus” menjual barang-barang sihir dan literatur, majalah bisnis terkemuka menerbitkan ramalan astro harga saham dan horoskop yang dirancang untuk membantu manajer puncak “beradaptasi” dengan perusahaan mereka. Pada jam tayang utama, saluran-saluran TV terkemuka menyiarkan rekayasa “tabib tradisional” dan “penyihir.” Para dukun TV dari program-program terkenal di akhir tahun 1980-an kembali mengudara dengan penuh kemenangan. Demi kebutuhan orang banyak yang mudah tertipu, paranormal bahkan ikut serta dalam “pertempuran” dan kompetisi.
Namun, penduduknya sendiri dengan senang hati bergegas ke pelukan para dukun dan paranormal. Menurut Rossiyskaya Gazeta, 11 hingga 13% penduduk Rusia sangat percaya pada ilmu sihir sehingga mereka siap untuk selalu meminta bantuan okultis. Di AS dan Kanada, angka ini berkisar antara 1 hingga 3%. Hampir 2/3 orang Rusia, pada prinsipnya, siap meminta bantuan dukun “jika terjadi keadaan hidup yang sulit”.
Jumlah pesulap profesional meningkat secara eksponensial. Menurut I. Trifonov, sekitar 100 ribu orang terlibat dalam pasar okultisme di ibu kota - penyihir dan dukun itu sendiri, asisten dan asisten mereka, aktor dan petugas keamanan, pengrajin yang membuat alat peraga dan agen yang mencari calon korban. Di Rusia setidaknya ada 300 ribu “spesialis” seperti itu (ada sekitar 2 ribu dukun yang terdaftar resmi dan berlisensi). Pendapatan dukun provinsi mencapai empat ratus ribu rubel sebulan, di Moskow - hingga satu juta. Pasar layanan okultisme, menurut berbagai sumber, di Moskow saja diperkirakan mencapai 8-10 juta dolar per bulan, di Rusia - hingga 40 juta (mungkin lebih). Menurut berbagai perkiraan, pendapatan tahunan para penyihir dan okultis di negara tersebut berkisar antara 1 hingga 5 miliar dolar.
Para okultis, tidak seperti psikolog dan dokter profesional, selalu menjamin hasil, sementara mereka tidak memikul tanggung jawab hukum maupun moral atas “konsultasi” mereka. Dan orang-orang yang tertipu sendiri terkadang mengaitkan “kegagalan” para okultis dengan “karma buruk”, kerusakan, dan mata jahat mereka.
Di negara kita, meskipun masalahnya jelas, tidak ada tanggung jawab administratif untuk penyediaan layanan magis. Sampai saat ini, satu-satunya pengecualian adalah Undang-Undang Wilayah Krasnodar tanggal 6 April 1999 No. 169-KZ, yang mengatur tanggung jawab administratif atas pelanggaran ketertiban umum, “dinyatakan dengan mengganggu warga untuk tujuan meramal dan mengemis. ” Secara berkala, media melaporkan upaya yang gagal oleh badan legislatif dari entitas konstituen federasi untuk memperkenalkan tanggung jawab administratif atas penyediaan layanan sihir. Sementara itu, tidak ada tanggung jawab administratif yang diharapkan, pasar layanan magis semakin berkembang dan menjadi lebih mahal.
Beragama tanpa agama sama dengan cita-cita masyarakat konsumtif dan kenyamanan. Ini adalah “permainan” agama, keadaan spiritual perantara yang memberikan ilusi keyakinan pada prinsip yang lebih tinggi dan sekaligus tidak mengikat pada apapun. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Rusia Vadim Rozin, “Media tidak hanya memberi informasi kepada seseorang, tetapi juga menciptakan realitas tertentu di mana mereka tenggelam. Dalam kerangka realitas – hampir virtual – seperti itu, tidak hanya pengalaman seseorang, tetapi juga pikiran dan sikapnya diprogram secara sadar, tetapi lebih sering secara tidak sadar.” Oleh karena itu, budaya massa, yang menjadi aliran informasi yang tiada henti, mengikis kesadaran beragama, dan juga budaya tradisional yang cukup stabil. Upaya untuk melibatkan spiritualitas klasik, “tinggi” dalam permainan dengan yang ajaib (dalam yang ajaib, luhur) dilakukan, khususnya, dalam seni massa modern, dalam pers kuning, dalam sinema dan sastra, misalnya, ketika simbol apa pun , konsep Ortodoksi bercampur dengan budaya “rakyat” primitif, takhayul, esoteris, gambaran okultisme, dll.
Permainan aneh ini mengarah pada transformasi sosiokultural yang serius - suatu sikap yang bisa disebut simulatif dan amorf (dari sudut pandang dunia batin seseorang, nilai-nilainya, kesadaran diri) religiusitas mulai mendominasi pikiran penonton. Pengusungnya rela berpartisipasi dalam permainan pemujaan massal terhadap keajaiban, “yang ilahi”. Secara umum, religiusitas baru dalam media merupakan latar belakang yang kaya akan sugestif dan mempunyai dampak serius terhadap khalayak media massa. Oleh karena itu, secara tidak kentara, namun cukup tajam, religiusitas semu memasuki kehidupan kita dan menjadi ciri kesadaran keagamaan umat modern.
Kesimpulan
Sebagai kesimpulan, saya ingin mencatat bahwa, dengan dipandu oleh maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam pendahuluan karya ini, kami menganalisis esensi kesadaran keagamaan orang Rusia dan tren perkembangannya.
Perlunya kajian ini sebagian besar disebabkan oleh situasi masyarakat modern saat ini, di mana kesadaran beragama mempunyai pengaruh yang semakin besar terhadap pembentukan pandangan dunia dan cara hidup masyarakat. Berdasarkan analisis terhadap kekhususan situasi teoritis-kognitif, kami sampai pada kesimpulan bahwa masalah kesadaran beragama belum cukup berkembang. Dalam hal ini, sejumlah arahan utama dalam studi kesadaran beragama telah diidentifikasi. Diantaranya adalah pengungkapan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hakikat dan kekhususan kesadaran beragama.
Setelah menelaah kondisi dan faktor munculnya kesadaran beragama, kami sampai pada kesimpulan bahwa hal-hal tersebut merupakan aktivitas sekelompok faktor, yang dapat diklasifikasikan dengan mengacu pada pertentangan logis “alami - sosial”.
Adapun hakikat dan struktur kesadaran beragama, telah kami ungkapkan bahwa komponen struktural utama kesadaran beragama dapat dibagi dalam dua arah: menurut proses pembentukannya - yaitu objek, subjek, isi, sarana, pengelolaan;
Dan menurut tingkat kognisi - alam bawah sadar, kesadaran biasa, kesadaran teoretis (teologi), kesadaran super, ideologi.
Saat ini masyarakat membutuhkan pengayaan spiritual dan keagamaan, sehingga ada kecenderungan beralih ke agama dan lembaga keagamaan. Ada “kebangkitan” kesadaran beragama. Namun berdasarkan temuan yang diperoleh, kami mencatat bahwa konversi “eksternal” terjadi ketika sisi “internal” sangat langka dan dipenuhi berbagai ketidakmurnian; dalam kesadaran keagamaan masyarakat, fenomena pseudo-religiusitas – yang diekspresikan dalam fenomena sinkretisme agama - kombinasi kepercayaan kepada Tuhan dengan kepercayaan pada pertanda, UFO, ilmu sihir dan sihir, dll.
Karena tersedianya dan meluasnya “pasar jasa magis”, karena cukup banyaknya pemberitaan fenomena ini di media, fenomena pseudo-religiusitas telah cukup tajam memasuki kehidupan kita dan telah menjadi ciri kesadaran beragama umat modern. .
Daftar sumber yang digunakan
1. Anishchenko A. I. "Struktur kesadaran publik." - M.: Lebih tinggi. sekolah, 1973. 88 hal.
2. Arinin E.I. “Filsafat Agama. Prinsip analisis esensial: Monograf". Arkhangelsk, 1998. - 297 hal.
3. Aristoteles. “Politik” // Aristoteles. Esai. Dalam empat volume. T.4. M., 1984, 377 hal.
4. Alkitab. Lembaga Alkitab Rusia M.: 2007. - 120 hal.
5. Borunkov 10. F. “Fitur kesadaran beragama.” M.: Pengetahuan, 1972. - 48 hal.
6. Borunkov Yu.F. “Struktur kesadaran beragama.” M.: Misl, 1971. - 176 hal.
7. Soal-soal filsafat. 1992. No. 7. Buletin Gereja Moskow. 1994, Nomor 7/104. S.3; 1995. Nomor 1/108. S.2.
8. Vorontsova L.M., Filatov S.B., Furman D.E. “Agama dalam kesadaran massa modern” // Penelitian Sosiologis. 1995.No.11.
9. Gavrilova Yu.V. “Sistem faktor alam dalam pembentukan kesadaran beragama”//Literasi. - 54 detik
10. Hegel G.F.V. “Kuliah Filsafat Agama.” Dalam 2 jilid. Ed. A.V. Gulygi. M., 1975.T.1.309 hal.
11. Golovin S.Yu. "Kamus Psikolog Praktis". - M.: AST, Panen. 1998.- 1089 hal.
12. James W. “Keanekaragaman Pengalaman Keagamaan”: Trans. dari bahasa Inggris -M.: Nauka, 1993.432 hal.
13. Eroshenkov M.G., Balaev V.V. "Pengantar Sihir Modern". M.: Dialog-MSU, 1998. - 288 hal.
14. Ilyin I.A. "Aksioma Pengalaman Beragama". M., 1993, - 41 hal.
15. Ionin L.G. "Postmodern: era magis baru." // Mode akses majalah Rusia< www.russ.ru/ist_sovr/20020514_ion.html >
16. Kanterov I. Ya “Gerakan keagamaan baru di Rusia. Analisa Keagamaan". - M., 2006.- 56 hal.
17. Filsafat Tiongkok. Kamus Ensiklopedis. M., 1994, 235-236s.
18. Terjemahan Alquran Osmanov M.-N.O. M.: Dilya, 2009.
19. Kolosnitsyn V. I. “Keterasingan agama.” Sverdlovsk: Rumah Penerbitan Universitas Ural, 1987. - 180 hal.
20. Kondratyev F.V. “Konsekuensi negatif sosial dari aktivitas formasi kultus” // Missionary Review. -1996. -№> 10.
21. Krapvensky S. E. "Filsafat Sosial". Volgograd: Komite Pers, 1995. - 352 hal.
22. Kulik V. S. “Tentang Metodologi Kajian Struktur Agama: Masalah Metodologi Pengetahuan Ilmiah” / Ilmiah. tr. Novosibirsk, universitas. Filsafat seri. Novosibirsk, 1986. - Edisi. 2. - hal.170-187.
23. Kyrlezhev A.I. “Tentang “pertanyaan” tentang peningkatan moral masyarakat dan ketertarikan Tuhan untuk ini” // Benua. 1995. - Nomor 85. -S. 263-277.
24.Kyrlezhev A.I. “Kesadaran beragama modern: antara fundamentalisme dan modernisme” // Pemikiran Rusia, Paris. 1999. - No. 4272. - 3 Juni.
25. Levada Yu.A. “Sifat sosial agama.” M.: Nauka, 1965.- 263 hal.
26. Lobovik B. A. “Menuju penilaian tingkat kesadaran beragama” // Filsafat. Sains. 1971. - No. 1. - Hal. 104-110.
27. Lobovik B. A. “Kesadaran beragama dan ciri-cirinya.” - Kyiv: Nauk, Dumka, 1986. 248 hal.
28. Pria A. “Sejarah agama.” Dalam 2 buku. M.: Rumah Penerbitan. kelompok "FORUM - INFRA - M.", 1998.
29. Milev V.A.: “Psikologi dan psikopatologi” // “Kedokteran dan pendidikan jasmani”, Sofia, 1988 – 15 hal.
30. Mitrokhin L. N. “Pengetahuan ilmiah dan agama pada pergantian abad ke-21” // Buletin Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, 2000. T. 70. - No. 1. - P. 320.
31. Muravyov Yu.A. “Agama sebagai fenomena budaya” // Budaya: teori dan masalah. M.: Nauka, 1995. - Hlm.212-239.
32. Mol A. “Sosiodinamika budaya.” – M.: Penerbit LKI, 2008. – 416 hal.
33. Buletin Gereja Moskow. 1994. Nomor 7/104/. S.3.
34.Mchedlov M.P. “Tentang religiusitas pemuda Rusia” // Penelitian Sosiologis. 1998.No.6.
35. Mchedlov M.P., Gavrilov Yu.A., Shevchenko A.G. Tentang potret sosial orang percaya modern // Penelitian Sosiologis. 2002. No. 7. hlm. 69–70.
36. Nikonov K. I. “Krisis agama dan modernisasi antropologis teologi Kristen” // Masalah terkini dalam teori dan praktik ateisme ilmiah. M.: Misl, 1985. - 64 hal.
37. Nikonov K. I. “Tentang pertanyaan tentang tingkat kesadaran beragama.” // Pertanyaan ilmiah ateisme. 1971. - terbitan. 2. - hal.230-242.
38. Novikova L.G. Ciri-ciri utama dinamika religiusitas penduduk // Penelitian Sosiologis. 1998.No.9.
39. Pembaruan Rusia: pencarian solusi yang sulit. Jil. 2.M„ 1994.Hal.151.
40. Paus Yohanes Paulus II "Penebus Umat Manusia". Mode akses http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/katholic/Veigel_papa/Veig_11.php
41. Peccei A. “Kualitas manusia”, Mode akses http://www.igrunov.ru/cat/vchk-cat-bibl/articles/peccei/
42. Prokofiev S. Ya.Kesadaran publik. Krasnodar: Krasnod. hukum Institut Kementerian Dalam Negeri Rusia, 1997. - 36 hal.
43. Pyrin A. G. “Lingkungan alam (analisis sosio-filosofis).” M., 2004. - 15 hal.
44. Radugin A.A. “Pengantar Ilmu Keagamaan.” – M.: Pusat, 2000. – 240 hal.
45. Rozin V.M. Ajaran dan praktik mistik dan esoteris di media // Ilmu sosial dan modernitas. 1997, No. 3. hal. 44-54.
47. Ryzhov Yu.V. Ignoto Deo: Religiusitas baru dalam budaya dan seni. Mode akses //http://www.binetti.ru/studia/ryzhov_11_2.shtml
48. Samygin S.I., Nechipurenko V.I., Polonskaya I.N. “Studi agama: sosiologi dan psikologi agama.” Tinggi. n/a: Penerbitan "Phoenix", 1996. - 672 hal.
49. Subbotina N. D. “Sosial di Alam. Alami dalam pergaulan.” M.: Prometheus, 2001.193 hal.
50. Spirkin A. G. “Asal Usul Kesadaran.” M.: Gospolitizdat, 1960. - 471 hal.
51. Spirkin A. G. “Kesadaran dan kesadaran diri.” M.: Gospolitizdat, 1972. - 303 hal.
52. Sukhov A. D. “Agama sebagai fenomena sosial.” (Masalah penelitian filosofis). M.: Mysl, 1972. - 143 hal.
53. Toshchenko Zh.T. “Tentang paradoks kesadaran sosial: aspek sosiologis” // Penelitian Sosiologis. 1995. N 1.
54. Ugrinovich D. M. “Masalah filosofis kritik agama. (Tentang kekhasan agama dan tempatnya dalam kesadaran masyarakat).” Ed. 2, tambahkan. dan pemrosesan M.: Penerbitan Mosk. Universitas, 1965. - 349 hal.
55. Uledov A.K. “Kehidupan spiritual masyarakat: Masalah penelitian metodologis.” M.: Misl, 1980. - 271 hal.
56. Uledov A.K. “Psikologi sosial dan ideologi.” M.: Mysl, 1985.268 hal.
57. Uledov A.K. “Struktur kesadaran publik.” Teori.-sosial. belajar. M.: Misl, 1968. - 324 hal.
58. Fromm E. “Psikoanalisis dan agama” // Fromm E. “Memiliki atau menjadi.” M., 1990. – 102 hal.
59. Huntington S.F. "Bentrokan Peradaban". – M.: M.: LLC “Rumah Penerbitan AST”, 2003. – 603 hal.
60. Shikhov G. L. “Rasa Sakit dalam Ritual” // Ilmu sejarah, filosofis, politik dan hukum, studi budaya dan sejarah seni. Pertanyaan teori dan praktek. Tambov: 2012. No.9 (23): dalam 2 bagian Bagian I. - 203-205 hal.
61. Yablokov I.N. “Pengantar Ilmu Keagamaan.” – M.: KDU, 2008. – 283 hal.
62. Yakovlev A.I. “Kesadaran beragama.” M.: Sputnik+, 2004, 37 hal.
Unduh: Anda tidak memiliki akses untuk mengunduh file dari server kami.
Filsafat tidak begitu banyak mempelajari ciri-ciri berbagai ajaran agama, melainkan religiusitas sebagai bagian dari bentuk kesadaran sosial dan individu. Agama merupakan salah satu fenomena kehidupan spiritual manusia dan masyarakat. Konsep filosofis agama ada dalam sistem Hegel, L. Feuerbach, K. Jung, E. Fromm; ada doktrin teologis (P.L. Berger); fenomenologis (T. Lukman), psikologis (Z. Freud), etnologis (B. Malinovsky), sosiologis (M. Weber,
E.Durkheim). Teori agama mengkaji tentang asal usul agama, unsur-unsur dan strukturnya, kegiatan keagamaan, hubungan keagamaan, organisasi, fungsi, peranan agama dalam masyarakat dan permasalahan lainnya. A. Schopenhauer percaya bahwa agama adalah metafisika, atau filsafat masyarakat, sebagai komponen pandangan dunia. Filsafat mempelajari agama sebagai pandangan dunia, mengungkap landasan sosial dan psikologis, makna ontologis dan epistemologis. Filsafat tertarik pada hubungan antara iman dan pengetahuan, masalah hubungan manusia dengan Tuhan, makna moral agama, perannya dalam kehidupan masyarakat, pada spiritualitas manusia dan kemanusiaan.
Teologi mempelajari kecukupan fakta kesadaran beragama yang diberikan dalam Wahyu. Pokok kajiannya adalah: Tuhan Yang Maha Mutlak dan hubungannya dengan manusia, alam, masyarakat, kemanusiaan.
Fungsi utama agama adalah pelayanan moral dan sosial: menabur perdamaian, cinta dan harmoni. Agama menghubungkan dua dunia: alam-sosial dan transendental. Keselamatan pribadi jiwa bergantung pada hubungan jiwa individu dengan yang transenden. Arti lainnya adalah retribusi. S. Frank percaya bahwa agama berarti keyakinan pada realitas nilai absolut, pengakuan terhadap prinsip yang menyatukan kekuatan wujud dan kebenaran ideal ruh. Tidak ada orang yang asing dengan kesadaran dan pengalaman beragama. Kata Latin "religio" berarti "kesalehan, kekudusan". Dalam agama ada bagian teoretis yang mengungkapkan konsep Yang Mutlak, yang menjadi sandaran segala sesuatu yang terbatas, dan ada bagian praktis yang memantapkan hubungan nyata Yang Mutlak dengan kehidupan manusia.
Yang Absolut dapat dipikirkan dengan cara yang berbeda. Agama tidak hanya melayani kebutuhan teoretis pikiran, tetapi juga tujuan moralitas, prinsip estetika, dan perasaan manusia. Kant mengatakan bahwa agama adalah moralitas, hukum yang hidup di dalam kita, suatu seruan terhadap pengetahuan tentang Tuhan. Hegel mengungkapkan dalam sistem filosofisnya objektifikasi Roh Absolut, pengungkapan diri manusia dalam bentuk gagasan. Hati manusia memerlukan agama.
Asal usul agama. Ada motif psikologis dan akar sosial dari agama; analisisnya mengungkapkan hubungan dengan pikiran manusia, moralitasnya, dan kebutuhan akan Wahyu. Jika religiusitas manusia dihasilkan oleh ketakutannya terhadap kekuatan alam yang tidak diketahui, ketika manusia mengungkap rahasia alam, maka religiusitas seharusnya menurun, namun hal ini tidak terjadi. Tentu saja, perasaan keagamaan masyarakat telah digunakan dalam sejarah untuk mengkonsolidasikan masyarakat dan memecah belah mereka demi tujuan politik, untuk memicu permusuhan, dan menyelesaikan masalah-masalah sosial. Fakta sejarah yang demikian tidak menjelaskan kemunculan dan keberadaan fenomena religiusitas. Oleh karena itu, penjelasan modern tentang perasaan keagamaan didasarkan pada psikologi agama; peneliti modern menunjuk pada mengakarnya perasaan keagamaan dalam pikiran manusia, di mana perasaan ini diberi tempat yang tetap.
Masalah mendefinisikan agama. Definisi yang diberikan oleh S.N. Trubetskoy dalam “Encyclopedia of Christianity” pada tahun 1899 hampir tanpa cacat: “Agama secara tentatif dapat didefinisikan sebagai pemujaan terorganisir terhadap kekuatan yang lebih tinggi. Pemujaan seperti itu, apakah itu pemujaan sensual, atau pelayanan dalam roh dan kebenaran, mengandaikan realitas yang tidak diragukan lagi bagi kesadaran beriman dari kekuatan-kekuatan lebih tinggi yang disembah. Pada saat yang sama, ini mengandaikan iman, yaitu. suasana keagamaan, yang diekspresikan dalam sistem pemujaan tertentu dan sistem gagasan tentang yang sakral.” Definisi ini hanya kurang memberikan penjelasan tambahan tentang apa itu “kekuatan yang lebih tinggi”, karena berbagai hal dapat diterima seperti: negara, akal, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.
E.A. Torchinov menganggap pengalaman transpersonal sebagai dasar agama, menurutnya berbagai pengalaman transpersonal tidak hanya menjadi dasar pengalaman beragama, tetapi juga agama itu sendiri.
Ada pendekatan yang berbeda terhadap hubungan antara agama dan sains, dari sudut pandang pengetahuan: pendekatan saintifik-positivis berangkat dari fakta bahwa agama adalah jenis pengetahuan yang paling rendah, takhayul, yang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan.
akan hilang; pendekatan historis-evolusi memandang agama sebagai bentuk pengetahuan yang dikembangkan yang selalu dilestarikan, bahkan sebagai bagian dari bentuk pengetahuan lain, pada tingkat yang lebih tinggi (di sini aspek agama yang lebih sensual dipertimbangkan); Pendekatan absolutis memandang agama dan sains sebagai dua pilihan yang sah, dua bentuk aktivitas spiritual manusia dan “mencari” batas-batasnya serta memahami kekhususan, hakikat dan maknanya bagi manusia dan masyarakat.
W. Heisenberg, pencipta mekanika kuantum, percaya bahwa esensi paling intim dari segala sesuatu bukanlah yang bersifat material, tetapi yang bersifat ideal. Newton mencari agama yang benar, pandangan dunia yang benar dan moralitas yang benar, yang tercermin dalam karyanya “Optics”. Kant percaya bahwa integritas dunia bersifat transendental.
Perhatian harus diberikan pada fakta bahwa, meskipun aspek indrawi mendominasi, keyakinan beragama tidak mungkin terjadi tanpa alasan. Sebagian besar ajaran filosofis abad ke-20, yang tidak menganggap dirinya religius, berakar pada agama; Filsafat agama modern juga mengalami perkembangan serius di banyak bidang. Agama menentukan kebaikan aktif, perilaku moral tertentu dan sikap terhadap kehidupan, manusia dan dunia.
Sayangnya penilaian di atas tidak berlaku pada semua bentuk atau situasi religiusitas. Selama masa-masa kritis dalam kehidupan seseorang dan dalam kondisi masyarakat yang berubah dengan cepat, sejumlah besar praktik spiritual semu muncul, yang sulit dinavigasi oleh seseorang. Para peneliti menulis bahwa saat ini, karena banyaknya dan inkonsistensi fenomena keagamaan yang ada, tidak ada definisi umum tentang agama.
Filsafat mempelajari kesadaran beragama sebagai salah satu jenis kesadaran manusia, atau sebagai jenis pandangan dunia, sebagaimana disebutkan di atas, W. Loeffler mendefinisikan kemungkinan isu-isu religiusitas bagi filsafat sebagai berikut: analisis dan artikulasi data keagamaan; penelitian terhadap pertanyaan tentang hakikat agama; analisis bahasa agama; memperjelas hubungan antara agama dan penjelasan dunia lainnya; membela ketidakwajaran atau kewajaran agama. Jelas bahwa permasalahan agama akan tetap relevan bagi filsafat selama masih ada pemeluknya.
Situasi sosial modern ditandai dengan semakin parahnya permasalahan keamanan nasional, negara, dan spiritual karena: 1) megatrend era modern adalah kejayaan individualisme yang menempati tempat sentral dalam masyarakat modern; 2) telah terjadi perubahan revolusioner di bidang informasi dan bioteknologi, yang menyebabkan fenomena krisis (kemungkinan mempengaruhi dan mengelola kesadaran individu dan sosial seseorang; 3) negara secara bertahap tidak lagi menjadi institusi dasar sistem politik dan politik. organisasi masyarakat; 4) komponen kreatif menguat dalam masyarakat pasca-industri. Isu hubungan antara agama dan ekonomi terus diperbarui. Proses Westernisasi atau bahkan Amerikanisasi semakin intensif, dan orientasi pro-Barat menjadi sebuah fetish. Terjadi unifikasi dan komersialisasi agama. Situasi keagamaan saat ini dalam kondisi tersebut bercirikan krisis.
Penemuan para astronom modern tidak hanya mengubah gagasan masyarakat tentang Alam Semesta, namun juga sikap mereka terhadap makna keagamaan tradisional. Oleh karena itu, “mengingat keagungan alam semesta yang luar biasa,” orang-orang percaya bahwa munculnya perasaan keagamaan tidak dapat dihindari. Pada saat yang sama, saat ini diketahui bahwa dunia lahir dan mati, mereka memiliki masa hidup mereka sendiri, seperti halnya manusia, bahwa di Kosmos juga terdapat banyak “penderitaan dan kematian, serta kelahiran dan kebahagiaan”; bahwa kehidupan dan pikiran adalah fenomena umum di Kosmos; bahwa kehancuran besar-besaran dan sering terjadi di seluruh alam semesta. Gambaran dunia ini bertentangan dengan pemahaman tradisional Barat tentang Ketuhanan, yang peduli terhadap kesejahteraan makhluk cerdas, dan lebih konsisten dengan gagasan agama Timur.
Dalam postmodernisme, proses kognisi tidak hanya dikaitkan dengan sains, tetapi juga dapat dikaitkan dengan agama, yang penting “demi kesejahteraan spesies manusia”. Pendekatan ini konsisten dengan banyaknya “agama baru” yang muncul sebagai akibat dari “serangan negara terhadap ajaran tradisional” dan “kompresi” atau “penghancuran ruang alami keberadaan mereka.” Negara sekuler yang menggusur agama dari ranah kehidupan spiritual, sebagaimana diperlihatkan sejarah, tidak menemukan pengganti yang memadai bagi perasaan beragama, oleh karena itu, dari perpaduan makna agama terlarang dan agama yang diakui secara resmi tetapi tidak aktif, muncullah ajaran-ajaran baru. Perwujudan aspirasi banyak postmodernis adalah agama “Zaman Aquarius”, atau “Zaman Baru” (secara harfiah: “zaman baru, abad”), yang konsep utamanya adalah monisme dan panteisme, dan sistem etikanya adalah berdasarkan pemahaman tentang kebebasan manusia yang tidak terbatas. Di sini dinyatakan bahwa segala yang ada dan yang tidak ada adalah satu: antara yang kita lihat dengan mata dan yang nyata ada,
hanya ada perbedaan nyata, yang “hanya ditentukan oleh persepsi”; semuanya adalah satu kesatuan, di mana manusia menjadi bagiannya. Karena Tuhan ada di dalam manusia, dan manusia adalah sejenis Tuhan, hal ini menimbulkan konsep khusus tentang dosa dalam agama New Age, atau lebih tepatnya, kurangnya pemahaman tentang dosa. Pengikut gerakan ini hanya mempertimbangkan konsep yang diperbolehkan dan tidak dapat diterima - orang itu sendiri yang menentukan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak dapat diterima. Segala sesuatu ditentukan oleh kesadaran manusia, yang merupakan bagian dari kesadaran bersama yang menyatu. Filosofi ini telah dikenal sejak zaman Gnostik, namun dalam agama New Age bentuknya lebih tegas dan radikal. Karena kesadaran tidak dapat dianalisis secara kritis dan kesimpulannya tidak dapat disangkal, maka pengalaman dan hati nurani memainkan peran utama. Merekalah yang akan menentukan konsep baik dan buruk, boleh dan dilarang, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang. Tidak ada yang secara umum buruk atau secara umum baik dalam agama yang dimaksud: dosa adalah sesuatu yang dikutuk oleh hati nurani seseorang dan tidak diperbolehkan untuk dilakukannya. Alkitab memberikan prinsip-prinsip umum untuk memandu situasi yang tidak dinyatakan dengan jelas. DG Likhikh merangkum pedoman berikut: jika seseorang ragu apakah mungkin untuk melakukannya atau tidak, maka lebih baik tidak melakukannya; seseorang tidak boleh menyalahkan tetangganya atas pilihannya; Anda tidak boleh memberikan kesempatan untuk menggoda tetangga Anda, agar tidak menyakitinya.
Yu.M. Antonyan menulis bahwa “bagi orang beriman, Tuhan adalah kenyataan yang tidak diragukan lagi” dan tidak memerlukan pembuktian. Oleh karena itu, Tuhan harus diakui sebagai fakta maya psikologis yang tidak terbantahkan dan dipelajari sebagai objek pengetahuan psikologis. F. Collins, seorang ahli biologi yang memainkan peran penting dalam menguraikan genom manusia, berusaha meyakinkan baik orang yang beriman maupun yang tidak beriman bahwa iman, meskipun sesuai dengan sains, adalah masuk akal, sedangkan ketidakpercayaan, meskipun sesuai dengan sains, adalah tidak masuk akal.
Ketika standar moral terkandung dalam doktrin agama, maka standar tersebut mengikat semua orang, namun kualitas ini hilang dalam masyarakat ateis. Moralitas berupaya mengatasi keterasingan keberadaan manusia baik dalam hubungan manusia satu sama lain maupun dalam kedudukannya dalam kaitannya dengan masyarakat, alam, dan cita-cita spiritual. Moralitas, tulis para penulis, lebih tua dari agama; spiritual juga mendahuluinya, karena agama muncul sebagai hasil dari pembentukan moralitas.
Modernitas, seperti yang ditulis banyak penulis, ditandai dengan munculnya meta-sains (yang muncul sebagai hasil integrasi filsafat, agama, dan ilmu-ilmu lainnya), yang mulai menggunakan metode yang sama dengan agama. Sebaliknya, pada pergantian abad 20 - 21, hampir semua agama besar mengadopsi program interaksi dengan masyarakat dan budaya sekuler. Timbul pertanyaan, pendidikan agama seharusnya seperti apa sekarang? Banyak perwakilan humaniora yang berbicara negatif tentang masuknya mata pelajaran ke dalam program pendidikan yang mempelajari dasar-dasar agama, dengan alasan bahwa dalam negara sekuler, agama dipisahkan dari negara, dan pendidikan adalah lembaga negara.
Di sini kita tidak bisa mengesampingkan keadaan ketika segmen pendidikan ini akan ditempati oleh disiplin ilmu lain, misalnya berdasarkan tipologi ruang paradigmatik I. Kolesnikova, yang di dalamnya terdapat realitas objektif, subjektif, dan transendental, aktivitas yang di dalamnya terkait. dengan menggunakan berbagai metode dan alat. Semuanya tidak berbahaya, namun dalam tiga paradigma pedagogi (berkaitan dengan tipologi ruang), paradigma terakhir disebut esoteris. Dalam pendekatan ini, pengetahuan tentang Tuhan tidak bersifat obyektif dan subyektif - pengetahuan ini mungkin mempunyai sumber yang berbeda-beda, namun pada dasarnya bersifat intersubjektif. Agama di sini mengungkapkan sumber pertumbuhan spiritual tertentu sebagai hadiah yang ditawarkan kepada seseorang. Itu. dalam hal ini kita berbicara tentang Agama Baru yang lain.
Kita juga tidak boleh meremehkan dampak “sekolah rahasia” terhadap perkembangan peradaban secara keseluruhan, karena, seperti yang mereka tulis, “semua kesempurnaan peradaban, semua pencapaian ilmu pengetahuan, filsafat dan seni adalah berkat lembaga-lembaga yang, dengan kedok kerahasiaan, berusaha menggambarkan kebenaran agama dan moralitas yang paling halus, untuk menanamkannya ke dalam hati para murid."
Pernyataan Winfield Loeffler bahwa, karena banyaknya fenomena dan sifat kontradiktifnya, tidak ada definisi umum tentang agama (baik pendekatan esensialis maupun fungsionalis runtuh; kita hanya dapat berbicara tentang “kemiripan keluarga”) dapat dikutip untuk mencirikan agama modern. situasi di Rusia. Namun pada hal ini, harus ditambahkan (satu
yang lain tidak mengecualikan) aktivitas yang lebih besar dari Gereja Ortodoks Rusia, yang mencoba berinteraksi dengan pihak berwenang dan cukup berhasil dalam aktivitas ini.
Saat ini, sifat-sifat Tuhan berikut diterima sebagai yang utama: transendensi, keberadaan yang diperlukan, karakter pribadi (kepribadian), kemahakuasaan, kemahatahuan, kemahahadiran, dll. tetapi bukan sifat-sifat khusus seperti trinitas, inkarnasi, dll.
Suprastruktur keagamaan terdiri dari kesadaran (termasuk gagasan, gagasan, perasaan dan suasana hati), pemujaan dan organisasi. Unsur utama tersebut tentu saja adalah kesadaran beragama (tindakan pemujaan, ritual keagamaan menjadi demikian karena mewujudkan keyakinan dan gagasan agama dalam bentuk simbolik. Organisasi keagamaan terbentuk atas dasar komunitas keyakinan agama.
Kesadaran keagamaan seolah-olah mewakili penggandaan dunia, karena, bersama dengan dunia nyata, keberadaan dunia lain diakui, di mana, menurut agama, semua kontradiksi keberadaan duniawi akan menemukan penyelesaiannya. Tanda utama kesadaran beragama adalah kepercayaan pada kekuatan gaib (terutama pada Tuhan sebagai pribadi yang diberkahi dengan kemampuan gaib, pada keajaiban dan keabadian jiwa, dan karenanya di akhirat).
Jika kesadaran sosial secara umum merupakan cerminan dari eksistensi sosial, lalu kesadaran beragama mencerminkan apa? Kesadaran beragama mencerminkan kontradiksi eksistensi sosial. Ini adalah kompensasi ilusi atas ketidakberdayaan praktis masyarakat, ketidakmampuan mereka mengendalikan kekuatan alam dan menyelesaikan kontradiksi sosial mereka sendiri. Hal ini terutama menentukan akar sosial dari agama.
Keterbelakangan tenaga-tenaga produktif, struktur sosio-ekonomi dan suprastruktur masyarakat, ketergantungan penuh manusia pada kekuatan-kekuatan unsur alam menjelaskan keberadaan awal supranatural bagi manusia dalam bentuk personifikasi unsur-unsur alam dan fenomena-fenomena yang menjadi jalan hidupnya. tergantung (agama pagan).
Belakangan muncul ketimpangan sosial, keterasingan ekonomi, dan ketergantungan tidak hanya pada alam, tetapi juga pada manusia. Marx menulis: “Kekuatan sosial, yaitu. kekuatan produktif berlipat ganda yang timbul karena aktivitas bersama berbagai individu akibat pembagian kerja, kekuatan sosial ini, karena aktivitas bersama itu sendiri tidak muncul secara sukarela, tetapi secara spontan, bagi individu-individu tersebut tampak bukan sebagai milik mereka. kekuatan yang bersatu, tetapi sebagai semacam kekuatan asing yang berdiri di luar kekuatan mereka, yang asal usul dan tren perkembangannya tidak mereka ketahui apa pun, oleh karena itu, mereka tidak dapat lagi mendominasi kekuatan ini - sebaliknya, yang terakhir sekarang melewati serangkaian kekuatan fase dan tahapan perkembangan, tidak hanya tidak bergantung pada kemauan dan perilaku masyarakat, tetapi sebaliknya mengarahkan kemauan dan perilaku ini.” Pada tahap inilah kekuatan agama yang menentang manusia menjadi manusiawi, yaitu. diberkahi dengan kualitas-kualitas kemanusiaan (disempurnakan), sampai ke penampilan, penampilan. Yang supernatural disubjektifikasi, dari paganisme, kesadaran keagamaan berpindah ke gagasan tentang satu tuhan sebagai pribadi (agama dunia yang berbeda memiliki tuhan tunggal mereka sendiri).
Akibatnya, akar sosial agama didasarkan pada perasaan tidak bebas, ketergantungan manusia pada kekuatan alam dan sosial.
Akar epistemologis agama mewakili kondisi, prasyarat, dan kemungkinan terbentuknya keyakinan keagamaan yang muncul dalam proses aktivitas kognitif manusia. Mereka terutama terletak pada kemampuan kesadaran untuk melepaskan diri dari kenyataan dan berfantasi. Setiap bentuk kognisi (sensasi, persepsi, ide, konsep, dll.) dapat menimbulkan prasyarat untuk refleksi palsu terhadap realitas. Jadi, ide tersebut sudah menciptakan peluang untuk mendistorsi dunia, untuk menciptakan gambaran-gambaran fantastis berdasarkan keterhubungan dalam kesadaran akan apa yang pada kenyataannya tidak dapat dihubungkan (misalnya, gambaran malaikat, setan, dll). Dalam pemikiran abstrak, suatu konsep, seperti diketahui, tidak sesuai dengan objek nyata: dalam generalisasi paling sederhana sudah ada momen fantasi tertentu. Hal ini dapat dilebih-lebihkan, dibesar-besarkan, dibingungkan. Ada pembagian dunia menjadi dunia nyata dan supranatural.
Akar psikologis agama meliputi berbagai keadaan emosi negatif manusia yang stabil, seperti ketakutan, kesedihan, kesepian, ketidakberdayaan, keputusasaan, serta pengaruh alam bawah sadar, tidak dapat dijelaskan, keinginan akan misteri, keajaiban pada seseorang.
Agama berbeda dengan idealisme karena agama didasarkan pada iman sehingga bersifat dogmatis. Idealisme adalah teori pengetahuan yang beroperasi dengan kategori epistemologis tertentu.
Agama melakukan beberapa fungsi:
fungsi ideologisnya terletak pada kenyataan bahwa agama menciptakan gagasannya sendiri tentang dunia, alam, masyarakat dan manusia, gambarannya sendiri tentang dunia;
fungsi kompensasi adalah kemampuan untuk mengisi kembali banyak aspek kehidupan yang penting bagi seseorang pada tingkat jiwa, kesadaran, emosi, dll;
agama menciptakan sistem norma dan nilai tersendiri yang mengatur perilaku manusia;
Fungsi komunikatif adalah memberikan kesempatan terjadinya komunikasi antar umat beriman yang dihubungkan oleh kesamaan pandangan dunia.
(c) Abracadabra.py:: Didukung oleh Investasikan Terbuka
Sergei Khoruzhy
"Seluruh paduan suara akan memberitahu Anda bahwa iman dan kebebasan berpikir adalah dua konsep yang saling eksklusif... Namun, mengapa mereka berpikir demikian? Tetapi karena semua konsep telah terdistorsi dan membingungkan." Yuri Samarin
1. Untuk memastikan bahwa jawaban-jawaban yang diberikan bukan sekedar kata-kata jurnalistik, maka perlu dibangun konteks dan kerangka konseptual. Pertanyaan-pertanyaan itu sendiri tidak menanyakannya. Mereka mengacu pada paradigma kuno dan tidak diartikulasikan dengan baik; namun jelas bahwa inti permasalahan yang dikemukakan adalah kesadaran beragama: sifatnya, situasinya di Rusia dan di dunia serta hubungannya dengan kesadaran kreatif.
Jadi - kesadaran beragama dan situasinya saat ini. Topik mengenai hal-hal tersebut relevan: baik realitas saat ini maupun, lebih jauh lagi, prospek yang muncul dengan jelas menunjukkan perlunya pemahaman baru mengenai hal-hal tersebut. Era ini merupakan sebuah tonggak sejarah dalam banyak hal, namun kita dapat dengan yakin mengatakan bahwa yang paling mendalam dan menentukan adalah perubahan antropologis. Jika sebelumnya keberadaan umat manusia lazim digambarkan sebagai proses perubahan sosio-historis yang mendominasi perubahan antropologis, kini hal tersebut semakin mustahil. Manusia sendiri mulai banyak berubah; ia semakin tidak lagi menjadi substrat, namun menjadi subjek, pahlawan perubahan yang sedang berlangsung, dan dinamika antropologi, yang semakin cepat, menjadi faktor utama. Tapi apa sifat, skala, batasannya? Pemahaman terhadap dinamika baru yang belum diketahui ini membawa kita ke pusat masalah Batasan Antropologis: batas-batas jenis dan cara keberadaan manusia, wilayah di mana ciri-ciri dan predikat yang sangat konstitutif dari metode ini mulai berubah.
Perbatasan Antropologis adalah konsep yang sulit. Jelas bahwa wacana mengenai perbatasan juga harus mengatakan sesuatu tentang Yang Lain, yang asing; wacana Perbatasan Antropologi harus dikonstruksi dari perspektif meta-antropologi. Dan di hadapan kita terdapat ontologische Differenz yang terkenal kejam, perbedaan antara ontik dan ontologis, yang ada dan yang ada. Apakah perspektif meta-antropologis diambil pada ontik atau ontologis, apakah yang asing itu merupakan sesuatu yang ada atau ada pada manusia? Jawaban: keduanya. Batasan Ontic jelas ada; seseorang secara ontik berada di luar batas – pengalaman kegilaan, pengalaman pelanggaran. Ada cukup banyak perhatian terhadap mereka saat ini; wacana Perbatasan ontik dikembangkan secara intensif oleh psikoanalisis dan arus pemikiran yang berdekatan. Tapi ini bukan keseluruhan Perbatasan. Ada pengalaman manusia di mana Batas itu berfungsi sebagai objek aspirasi, diuji, dan dicapai sebagai batas eksistensial, batas transformasi predikat fundamental cara hidup yang ada. Dialah yang menempati kita. Sebab wacana yang bertemakan Perbatasan Antropologi sebagai perbatasan ontologis adalah wacana kesadaran beragama. Dengan kata lain, kesadaran beragama dapat diartikan sebagai kesadaran (dispensasi, struktur kesadaran), yang memiliki perspektif ontologis, atau meta-antropologis (yang dalam konteks kita sinonim).
Kesadaran beragama terungkap dalam berbagai wacana, membangun perekonomian yang bercabang: dalam teologi, filsafat, mistisisme, pemujaan, praktik spiritual... Dalam kerangka perekonomian ini, “iman” dibentuk, “Gereja” dibentuk. Setelah mendefinisikan kesadaran keagamaan “dalam wacana energi”, secara penuh semangat dan aktif, sebagai suatu jenis strategi, kita harus memikirkan kembali fenomena ini juga dalam wacana ini. Apa itu "iman"? - mengikuti “strategi percaya”: strategi yang memadai untuk jenis organisasi energi khusus yang melekat dalam perspektif meta-antropologis - sistem sinergis, dalam kamus Ortodoksi, atau rezim sinergis, dalam kosakata sains (“memadai ” artinya: berorientasi pada mereka, tetapi secara umum belum tentu menjadi milik mereka lagi). Dalam wacana esensialisasi yang umum dalam pemikiran Eropa, “iman” direduksi menjadi isi yang substansial dan diidentikkan dengan penerimaan sewenang-wenang terhadap proposisi-proposisi tertentu yang tidak dapat dibuktikan; tetapi bahkan ketika iman itu sendiri merangkum dirinya dalam sebuah Kredo tertentu, yang tampaknya merupakan seperangkat postulat esensial, bukan suatu kebetulan bahwa Kredo tersebut menyandang nama “Pengakuan Iman”: itu sama sekali bukan iman itu sendiri, tetapi apa yang melambangkannya, sistem dari tanda-tanda simbolisnya. Demikian pula “Gereja” di sini tampil sebagai realisasi intersubjektivitas dalam perspektif meta-antropologi. Yang terakhir ini memperkenalkan perbedaan mendasar dari intersubjektivitas biasa. Intersubjektivitas, yang dilakukan dalam tematisasi ontologis Perbatasan Antropologi, menghadapi masalah integritas dan kelengkapan dan, dalam tematisasi predikat ini, mengkonseptualisasikan dirinya sebagai aporia (lih. identifikasi aporia integritas dalam analisis eksistensial) meta-empiris pan -subyektivitas. Dengan demikian, ia bukan lagi sekedar ruang komunikasi atau komunikasi wujud yang dialogis, melainkan semacam komunikasi wujud yang menyatukan ciri-ciri Gereja mistik dan Gereja historis. Subjektivitas antar-pan yang bertema ontologis ini ternyata dekat dengan konsep konsiliaritas dalam pengembangan awalnya oleh Khomyakov.
2. Ini adalah kerangka perkiraan atau, jika Anda suka, rimpang dari kesadaran beragama. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan hubungannya dengan prinsip kebebasan, budaya, kreativitas; dan prinsip-prinsip ini, sebagaimana dapat dilihat dari produksi, semuanya dianggap bertentangan dengan produksi, sebagai hal yang lain. Namun, pemahaman seperti itu – kita harus mulai dari sini – bukan saja tidak diperlukan, namun juga primitif dan ketinggalan jaman, sesuai dengan paradigma Pencerahan yang sudah lama ketinggalan jaman. Keusangan, bahkan bahaya, pandangan ini terletak pada dua ciri utama: pandangan ini berkaitan dengan pemikiran ideologis dan biner, yang, seperti kesadaran primitif, berdiri di atas oposisi biner dan dikotomi realitas. Tugas deideologisasi dan dekonstruksi struktur-struktur tersebut relevan untuk semua bidang kesadaran dan budaya, baik religius maupun non-religius. Pendekatan “wacana energi” yang digambarkan adalah salah satu cara untuk melakukan hal ini; dia asing dengan ideologi dan biner sejak awal. Kesadaran beragama pada hakikatnya tidak bersifat ideologis, tetapi strategis, tidak menjalankan fungsi mendikte, tidak berperan sebagai “pembatas kebebasan”, tetapi menjalin hubungan khusus wacana-wacananya dengan wacana mana pun di luar lingkupnya. sebagai hubungan praktik, jenis struktur energi; dan dalam hubungan seperti itu, kriteria kedekatan atau keterasingan, kecocokan atau ketidaksesuaian bukanlah bersifat ideologis, melainkan antropologis, personal, dan operasional. Seperti, katakanlah, fakta yang sudah lama diketahui tentang sulitnya kecocokan, ketegangan dalam hubungan kesadaran beragama dengan seni akting, akting, tidak berakar pada ideologi, tetapi pada perbedaan mendalam dalam strategi pribadi. Ada ketegangan penting lainnya. Realisasi diri yang murni dan maksimal atas kesadaran beragama adalah praktik spiritual. Ini adalah wacana atau strategi yang bersifat khusus, “praktik diri” holistik yang melakukan pengorganisasian langkah demi langkah dan transformasi seluruh kompleks energi manusia ke dalam sistem sinergis tersebut. Untuk wacana total seperti itu, kombinasinya, kesesuaiannya dengan wacana lain adalah sebuah masalah: dan ini adalah ketegangan yang dikenal sejak zaman kuno, keberbedaan timbal balik dan polaritas dari "prestasi", "biara" - dan "dunia", "spiritual" dan "sekuler". Ketegangan ini seharusnya membuahkan hasil, sebagai indikasi “dunia lain” yang membangunkan “dunia”, namun juga bisa berakibat destruktif...
Secara apriori, kesadaran beragama lebih bebas dibandingkan kesadaran non-religius; secara de facto sering kali ternyata kurang gratis. Ia lebih bebas, karena memiliki perspektif meta-antropologis, ia memiliki rentang realisasi diri yang berbeda secara fundamental dan tiada bandingannya. Namun selalu ada bahaya tergelincir ke dalam wacana esensial - objektifikasi iman, pelembagaan Gereja - dan kemudian berubah menjadi kesadaran, dalam arti buruk, dogmatis, salah satu jenis kesadaran yang paling tidak bebas. Adapun mengenai “kebudayaan”, “kreativitas”, “kesadaran kreatif”, sebelum memperjelas sikap agama terhadap mereka, ada baiknya dicermati bahwa saat ini mereka memang perlu memperjelas hubungannya dengan diri mereka sendiri. Oposisi Agama - Budaya sesuai dengan kenyataan dan mengungkapkan rumusan masalah di dunia sebelum Perang Dunia Pertama - sama-sama di Barat dan di Rusia, di mana Zaman Perak mengabdikan koleksi, malam, dan bacaan yang tak terhitung jumlahnya untuk masalah ini demi ketidakcukupan pelajar dan prajurit yang lumpuh. Sejak itu, banyak tinta mengalir, dan bahkan lebih banyak darah. “Budaya” tidak lagi diucapkan dengan aspirasi - kecuali mungkin di kantor redaksi Znamya. “Budaya adalah sebuah kepala yang busuk,” kata Andrei Bely saat itu. “Saya tidak suka kata sombong ini,” kata Pasternak di tahun 50an. Kemudian pembenaran untuk keangkuhan menjadi semakin berkurang, dan kebusukan menjadi semakin besar. Saat ini, permasalahan budaya yang pertama bukanlah pada hubungannya dengan kesadaran beragama, melainkan pada proses disintegrasi mendalam dari kesadaran diri. Semantiknya sendiri telah bergeser, bilangan tunggal telah berubah menjadi bunyi kosong, flatus vocis, dan terdapat budaya dan praktik - nat, seks, krimi dan semua minoritas lainnya, praktik pelanggaran, budaya jamur, bakteri ... - dan menurut prinsip penguasa tertinggi P.C., semua budaya adalah setara, tetapi beberapa budaya - pada saat feminisme dan pelanggaran ini - terasa lebih setara. Setelah membalikkan tetractys Hellenic, kuadrat permulaan kosmos kuno, postmodernitas menegaskan kuadrat ujungnya: Kematian Tuhan - Kematian Subjek - Akhir Sejarah - Akhir Teks. Jelas bahwa rangkaian kematian ini mengandung lebih banyak lagi; dan Kematian Kreativitas juga harus dimasukkan dalam rangkaian kematian yang lengkap. Seperti semua wacana postmodernis, tesis-tesis tersebut bukannya tanpa dilebih-lebihkan, bukan tanpa retorika yang mengejutkan - namun pada intinya, tesis-tesis tersebut tidak salah.
Pertentangan lama tidak membantu untuk memahami penyakit sampar yang umum ini. Matinya kreativitas, seperti semua hal lainnya, bukan disebabkan oleh intrik kesadaran keagamaan. Kita harus kembali ke apa yang dikatakan di awal: zaman sedang mengalami pergeseran tektonik yang radikal, dimana kita tidak hanya berbicara tentang perubahan “paradigma budaya” atau “formasi sosial”. Di balik semua struktur sosial dan politik, di balik arah dan paradigma kebudayaan, terdapat apa yang sebelumnya dipandang sebagai substrat, tidak bergerak, berubah hanya dari “perubahan di atas”: manusia itu sendiri. Dia bukan sebuah fenomena atau noumenon, bukan sebuah “dasar” atau “superstruktur,” dia adalah fokus dari realitas dan hubungan-hubungannya, awal dari hubungan. Fokus realitas ini mulai berubah. Pria itu mulai bergerak - dan mereka ikut bergerak, semua tingkat, lantai, dan atap pun ikut bergerak. Dinamika antropologis lebih diutamakan daripada dinamika sosial dan budaya: milenium Manusia itu sendiri akan datang. Di sini kita tidak dapat membahas esensi dari dinamika, pergeseran antropologis, yang mencakup segala sesuatu - somatik, jiwa, persepsi, kecerdasan - tetapi kita dapat melihat vektornya: tentu saja, diarahkan ke Perbatasan Antropologis. Pengalaman Borders menempati lebih banyak ruang dalam pengalaman manusia. Perbatasan sedang diuji, diperiksa dengan lebih dan lebih gigih, lebih penuh semangat, lebih dekat; dan kami memahami bahwa seluruh rangkaian kematian postmodern juga merupakan bagian dari proses ini, buah dari keinginan untuk mencapai Perbatasan.
Jadi, praktik atau strategi Boundary menjadi yang terdepan. Strategi tersebut ada tiga jenis: strategi virtual (Perbatasan sebagai realitas virtual yang tidak terwujud) - strategi Alam Bawah Sadar (Perbatasan ontik, atau bidang "kegilaan") - strategi keagamaan (Perbatasan ontologis, atau meta-antropologis). Dan merekalah yang akan memainkan seluruh permainan Milenium Ketiga di antara mereka sendiri. Dalam kombinasi dan interaksinya, segala bentuk realisasi diri manusia memperoleh tampilan baru; dan Kreativitas dan Agama membangun kembali hubungan, melayani bersama di Perbatasan. Perbedaan dan ketegangan di antara mereka akan tetap ada: tercermin sebagai strategi batas, mereka tetap merupakan strategi yang berbeda karena kreativitas sama sekali tidak mengasosiasikan dirinya hanya dengan Batas ontologis dan tidak berorientasi murni pada perspektif meta-antropologis. Namun perbedaan mendasarnya, hubungan mereka tentu tidak akan bersifat oposisi biner, berpindah dari paradigma ideologis ke paradigma dialogis. Setelah melewati kematian dalam postmodernisme, kreativitas pun menyerap pengalaman Batasan ontologis, dan tidak lagi memandang “dunia lain” sebagai gerbang baru; “Kelahiran pembaca” yang ditemukan dalam “kematian penulis” sudah memiliki kemiripan tertentu dengan paradigma praktik Spiritual. Dan hubungan dialogis antara kesadaran kreatif dan keagamaan ini merupakan syarat yang menentukan sifat dinamika antropologis yang non-bencana: agar Manusia, setelah memulai, tidak berpindah ke dalam kegilaan dan ketiadaan, melainkan ke dalam ruang kehidupan dan akal baru.
3. Dalam diskusi kami, kami belum menyentuh karakteristik Rusia sama sekali - dan ini dibenarkan, karena karakteristiknya tidak begitu penting (selain itu, ketika mengkonsep bidang kesadaran beragama, kami sebagian dipandu secara khusus oleh tipe Ortodoks). religiusitas). Semua ciri-ciri umum, unsur-unsur utama dari situasi dan permasalahan keagamaan adalah sama, dan realitas Rusia hanya menambahkan rincian dan citarasanya sendiri ke dalamnya: cita rasa keparahan yang menyakitkan, krisis yang lebih tajam dari semua proses dan semua konflik. Ciri utama dari cara hidup, reproduksi tradisi spiritual, adalah pergulatan antara kecenderungan protektif dan pembaruan, “konservatisme” dan “modernisme.” Perjuangan ini adalah faktor yang paling terlihat dalam situasi keagamaan saat ini, sebuah faktor yang alamiah, tak terhindarkan dan menyehatkan. Namun di dalamnya ditambahkan dua faktor lain: krisis mendalam yang menyeluruh - kekuasaan, ekonomi, lingkungan sosial budaya, serta keterbelakangan ekstrim dalam kehidupan beragama itu sendiri, yang baru kemarin secara paksa direduksi oleh totalitarianisme menjadi sepasang primitif. bentuk, institusi ritual ditambah hierarki perbudakan. Akibatnya, kedua kutub, “konservatisme” dan “modernisme”, disajikan dalam versi yang buruk, sehingga mempermalukan sejarah spiritual negara. Lebih lanjut: sekali lagi, bukan hanya ciri khas Rusia yang muncul saat ini “konservatisme”, pertama-tama, dalam bentuk anti-ekumenisme, dan anti-ekumenisme sedang mengalami pertumbuhan dan kebangkitan yang jelas. Di sini Gereja Rusia dan Rusia mengikuti arus utama tren pan-Ortodoks; dan meskipun ada faktor internal yang mendorongnya, hal ini tidak begitu terasa di negara kita seperti di Serbia atau bahkan Yunani.
Namun apakah fitur-fitur ini sangat terkait dengan topik kita? Adalah suatu kesalahan untuk mengikuti jalan yang sudah jelas, dengan menganggap “konservatisme” sebagai hambatan yang tidak ada artinya bagi kesadaran kreatif dan “modernisme” sebagai jalan keluar yang baik untuk itu. Tidak ada keraguan bahwa pasukan keamanan Rusia saat ini akan dengan rela melarang segala sesuatu yang pernah dilarang atau hanya ingin dilarang oleh Katkov, Pobedonostsev, dan A.P. Tolstoy; Namun, “modernisme” tidak mengedepankan sesuatu yang kreatif, hanya bersifat tiruan dan dangkal. Seperti biasa, tugas spiritual yang sebenarnya berada di luar biner yang cacat, dan esensinya saat ini juga jelas: ini adalah pemulihan tradisi intelektual Ortodoksi yang otentik, “wacana Kristen Timur.” Berdasarkan patristik klasik dan antropologi asketis, yang dikembangkan dalam teologi energik Byzantium, wacana ini tidak dialihkan ke Rus - yang menjadi salah satu alasan utama kelemahan fatal dan anorganik budaya keagamaan di Rusia, kesenjangan antara Ortodoksi dan pencerahan. . Namun, di diaspora, pemikiran Rusia dan Gereja dengan cemerlang memulai perkembangan modernnya, yang mengungkapkan kekayaan dan relevansi model manusia yang tertanam di dalamnya, kesesuaiannya dengan banyak kesimpulan dari pengalaman modern. Pekerjaan yang berhasil dimulai harus dilanjutkan di tanah Rusia; dan di sini, dalam kelanjutan ini, kesadaran kreatif dan religius dapat bersama-sama menemukan cara untuk memahami pergeseran yang kini terjadi dalam fokus realitas yang misterius: pada manusia.
G.I.Uspensky. Penuh koleksi op. dalam 14 volume - M.,
1949.- T. 8.- P. 385, 388 (“Mau tak mau”).
1. Prasyarat dan syarat munculnya kesadaran beragama. Pembentukan dan evolusi gagasan tentang supranatural.
Kesadaran beragama: objek refleksi, ciri dan kekhususan.
Struktur dan fungsi kesadaran beragama.
Kesadaran beragama modern: konservatisme dan tren perubahan.
PERKENALAN
Setiap orang, dalam proses mengumpulkan pengalaman hidup, mengembangkan minat tidak hanya pada perwakilan bangsanya sendiri, tetapi juga pada perwakilan bangsa, negara, kepercayaan dan agama lain. Seringkali, orang tertarik dengan penampilan, tindakan spesifik, perilaku, dan gaya hidup mereka.
Seni, sains, dan agama telah lama dikaitkan dengan pemikiran mitologis dalam sejarah manusia. Bahasa tersebut memuat rumusan umum gagasan dan hukum yang hidup dalam jiwa masyarakat, hubungannya. Mitos dalam arti luas adalah pandangan dunia primitif dan permulaan agama, isi asli gagasan.
Permasalahan kesadaran beragama di kalangan penganut agama yang berbeda, serta kekhasan perkembangan hubungan kebangsaan baik dalam suatu bangsa maupun antar bangsa, cukup relevan. Dalam proses sejarah etnis, kebutuhan dan kepentingan baru selalu muncul dan terbentuk, untuk memenuhinya masyarakat nasional terpaksa mencari sumber daya, menciptakan sumber daya baru, dan mencapai redistribusi. Dalam proses persaingan antaretnis dapat timbul kontradiksi dan perselisihan antar masyarakat dan bangsa.
Objek karya ini adalah bangsa dalam arti luas.
Subyek - ciri-ciri kesadaran beragama dan ciri-ciri hubungan kebangsaan.
Tujuannya untuk mengetahui ciri-ciri kesadaran beragama dan ciri-ciri hubungan kebangsaan.
Tujuan: mengetahui kekhususan kesadaran beragama; mengidentifikasi ciri-ciri kesadaran beragama dalam masyarakat modern; menunjukkan ciri-ciri psikologis bangsa, landasan psikologisnya; mengungkap ciri-ciri perkembangan hubungan nasional; menganalisis literatur yang diperlukan tentang masalah ini.
1. Prasyarat dan syarat munculnya kesadaran beragama. Pembentukan dan evolusi gagasan tentang supranatural
Tahap-tahap awal pembentukan kesadaran beragama, serta agama secara umum, tersembunyi di balik tebalnya tahun-tahun yang telah berlalu di planet kita. Agama bukanlah sesuatu yang melekat pada diri manusia. Ada masa pra-agama. Masa ini menurut para ilmuwan berlangsung sangat lama, hingga berakhirnya zaman Paleolitik Bawah (masa awal Zaman Batu Tua), meliputi zaman Mousterian (sekitar 100 - 40 ribu tahun yang lalu), ketika masa- disebut manusia Neanderthal yang hidup dengan berburu beruang gua dan hewan lainnya. Pemakaman Neanderthal, yang ditemukan dan dipelajari oleh para arkeolog, belum memberikan bukti yang tak terbantahkan akan adanya gagasan keagamaan di kalangan nenek moyang purba tersebut. Meski para ahli tidak menutup kemungkinan bahwa penguburan orang mati bisa menjadi salah satu sumber terbentuknya gagasan tersebut. Para ahli agama mengasosiasikan kemunculan agama dan munculnya kesadaran beragama, seperti disebutkan sebelumnya, dengan zaman Paleolitikum Atas (sekitar 40-18 ribu tahun yang lalu), ketika manusia modern (Homo sapiens) muncul, dengan mengacu pada temuan arkeologis.
Sebagian besar peneliti fenomena agama cenderung berpendapat bahwa memahami kemunculan dan perkembangannya dapat dilakukan, pertama-tama, melalui analisis hubungan antara masyarakat dan alam pada saat terbentuknya masyarakat itu sendiri. Menunjuk pada sifat spesifik mereka, sarjana agama Italia A. Donini menarik perhatian pada fakta bahwa hubungan antara manusia dan alam, yang terjalin sejak dahulu kala, selalu memiliki karakter ganda: dominasi alam yang mahakuasa atas manusia yang tidak berdaya, pada alam. di satu sisi, dan, di sisi lain, dampak terhadap alam, yang berusaha diwujudkan manusia, bahkan dalam bentuk-bentuk terbatas dan tidak sempurna yang menjadi ciri masyarakat primitif, dengan menggunakan peralatannya, tenaga produktifnya, dan kemampuannya.
Dominasi alam yang mahakuasa atas manusia yang tidak berdaya pada saat itu, sebagaimana diyakini sebagian besar peneliti yang menganut pandangan dunia materialistis, bertanggung jawab atas munculnya agama dan kesadaran beragama.
Benar, ada sudut pandang lain. Jadi, misalnya, membelanya, Yu.A. Levada berpendapat bahwa agama tidak bisa berasal dari “ketidakberdayaan” manusia, karena religiusitas bukanlah pendamping yang sangat diperlukan dalam keterbatasan kekuatan dan pengetahuan kita. Menurutnya, tepat jika kita menganggap fungsi agama tidak dibandingkan dengan kebutuhan kodrati apa pun, tetapi dengan kebutuhan sistem sosial yang spesifik secara historis. Tampaknya pendapat seperti itu hampir tidak dapat dianggap sah, karena pendapat ini didasarkan pada pertentangan artifisial antara kebutuhan alami manusia dan kebutuhan sistem sosial yang spesifik secara historis, meremehkan peran sistem sosial dan absolutisasi, hiperbolisasi sistem sosial. Sementara itu, kebutuhan pertama dan kedua mencerminkan aspek-aspek yang terkait erat dari satu kesatuan - antropososiogenesis. Mereka tampil sebagai sepasang dialektis yang berlawanan, yang hubungan di antaranya, tidak hanya dicirikan oleh saling negasi, namun juga oleh saling ketergantungan, saling melengkapi, kedudukan bersama, berfungsi dan terus berfungsi sebagai sumber pembentukan dan perkembangan baik manusia maupun masyarakat, sehingga menentukan perkembangan aktivitas manusia sebagai manifestasi spesifik dari materi gerakan sosial dan hasil-hasilnya, “sifat kedua”, yaitu kebudayaan, yang salah satu unsurnya adalah agama.
Oleh karena itu, ketika menganalisis proses pembentukan dan perkembangan agama dalam suatu masyarakat tertentu, perlu mempertimbangkan baik kebutuhan individu maupun kebutuhan sistem sosial yang spesifik secara historis, yang, karena berada dalam kesatuan dialektis, tentu saja menerima. refleksi yang sesuai dalam bentuk-bentuk keagamaan yang muncul. Perlu dicatat bahwa perhatian K.Marx. Berbicara tentang komunitas kuno, ia secara khusus menekankan: “Kondisi keberadaan mereka adalah rendahnya tingkat perkembangan tenaga produktif kerja dan keterbatasan hubungan masyarakat dalam kerangka proses material produksi kehidupan, dan oleh karena itu keterbatasan seluruh hubungan mereka satu sama lain dan dengan alam. Keterbatasan nyata ini idealnya tercermin dalam agama-agama kuno dan kepercayaan masyarakat yang memuja alam.”
Berbagai penelitian etnologi oleh E. Taylor, J. Fraser, I.A. Kryveleva, S.A. Tokarev dan penulis asing dan dalam negeri lainnya membantu merekonstruksi sejarah munculnya kepercayaan agama, memberikan bahan perbandingan yang luas untuk menjelaskan persamaan mitos, kepercayaan dan aliran sesat di antara masyarakat dari berbagai negara, benua yang berbeda, yang berasal dari kesamaan agama. kebutuhan dasar manusia, bentuk kegiatan produksi, cara hidup mereka pada tahap awal sejarah perkembangan umat manusia. Materi yang diperoleh peneliti memungkinkan untuk mengidentifikasi hubungan antara kesadaran beragama dengan perkembangan bahasa dan perkembangan umum budaya dunia kuno.
Para ilmuwan memasukkan mania dan fetisisme, totemisme dan animisme, kultus pertanian dan perdukunan, yang muncul selama pembentukan dan pengembangan sistem kesukuan (dari 100 ribu hingga 40 ribu tahun yang lalu), sebagai bentuk awal agama. Sihir adalah tindakan dan ritual yang dilakukan manusia primitif dengan tujuan mempengaruhi fenomena alam, hewan, atau orang lain secara supernatural. Manusia primitif dicirikan oleh pemujaan terhadap berbagai benda, yang menurutnya dianggap dapat menangkal bahaya dan membawa keberuntungan. Bentuk keyakinan agama ini disebut fetisisme. Kepercayaan terhadap kekerabatan supernatural kelompok manusia primitif (klan, suku) dengan spesies hewan dan tumbuhan tertentu (lebih jarang dengan fenomena alam dan benda mati) mendasari bentuk keagamaan awal seperti totemisme. Kepercayaan akan keberadaan jiwa dan roh menentukan keberadaan animisme (dari bahasa Latin anima, animus - jiwa, roh). Sistem ritual dan gagasan keagamaan dan magis yang terkait dengan pertanian dan bertujuan untuk memastikan dan melestarikan tanaman dengan meminta bantuan roh dan dewa membentuk kultus pertanian atau agraria. Serangkaian ritual dan ritual khusus yang terkait dengan kepercayaan pada kemampuan supernatural dan kemampuan pendeta menjadi dasar perdukunan.
Seiring berjalannya waktu, bentuk-bentuk agama suku yang utama digantikan oleh agama-agama etnis, yang kadang-kadang disebut agama nasional atau negara-bangsa. Secara khusus, ini termasuk:
Agama Yunani kuno, yang, pada zaman kuno, sebagaimana dibuktikan oleh sumber-sumber, dicirikan oleh penghormatan khusus orang Yunani terhadap ibu pertiwi. Dewi Gaia dianggap oleh mereka sebagai ibu dari semua makhluk hidup. Kultus leluhur juga sangat penting, yang juga dikaitkan dengan kultus pahlawan - setengah manusia, setengah dewa. Pada milenium ke-2 SM. dewa-dewa lokal kecil disingkirkan dan jajaran dewa akhirnya terbentuk, dipimpin oleh Zeus, "bapak manusia dan dewa", yang dalam bentuk religius mewujudkan ciri-ciri penguasa patriarki, kepala "keluarga" para dewa, yang kedudukannya dianggap menjadi Gunung Olympus. Pada abad VIII-VII. SM. Kuil pertama mulai dibangun untuk menghormati para dewa. Ada juga perkumpulan keagamaan dan aliran sesat rahasia di Yunani Kuno.
Agama Mesir kuno adalah sistem kepercayaan politeistik suku dan masyarakat Lembah Nil, di mana pemujaan terhadap alam memainkan peran besar. Sungai Nil, yang menjadi sumber banjir kesejahteraan negara, dipersonifikasikan dalam gambar dewa Hapi, matahari - dalam gambar dewa Ra, dewi Sokhmet digambarkan dalam bentuk sapi, dewa pembalseman Anubis - dengan kepala serigala. Hewan dengan warna tertentu dinyatakan sebagai inkarnasi dewa, tinggal di kuil dan menjadi objek pemujaan. Agama Mesir kuno sangat dipengaruhi oleh pemujaan terhadap orang mati. Gagasan tentang dewa tertinggi di Mesir dibentuk dalam gambaran penguasa firaun di bumi, yang dianggap sebagai putra dewa dan dewa yang hidup di bumi.
Agama India kuno adalah keyakinan agama yang berkembang dari kepercayaan primitif era pra-Arya hingga pemujaan terhadap banyak dewa yang mempersonifikasikan kekuatan alam. Invasi Arya ke India menyebabkan penyatuan berbagai aliran sesat. Agama Weda berjumlah sekitar 3 ribu dewa. Kepala para dewa dianggap Varuna, yang dalam mitos sering diidentikkan dengan langit (Dyaus) dan diberkahi dengan kualitas penjaga ketertiban dan keadilan. Namun, satu pun dewa dewa belum terbentuk selama periode ini. Upaya untuk menciptakannya hanya dilakukan menjelang akhir periode Weda. Di dalamnya, dewa Brahma menempati tempat yang sederhana, hanya mengawasi kebenaran pengorbanan. Pada pergantian milenium pertama SM. agama India kuno diubah menjadi Brahmanisme. Dewa-dewanya termasuk dalam jajaran agama baru, tetapi di latar depan adalah Brahma, dewa pencipta dunia dan personifikasi alam semesta.
Agama Tiongkok kuno, yang merupakan seperangkat keyakinan agama dan pemujaan masyarakat di lembah sungai Kuning dan Yangtze, dicirikan pada milenium ke-2 hingga ke-1 SM. adanya pemujaan animik terhadap roh alam dan pemujaan terhadap nenek moyang. Dengan munculnya masyarakat klasik, gagasan tentang hierarki roh terbentuk, dipimpin oleh roh surga Shandi - bapak manusia, yang, merawat mereka, memberi penghargaan kepada sebagian orang dan menghukum orang lain. Orang Tiongkok kuno juga menyembah “roh bumi” - roh gunung dan sungai. Roh duniawi Khoutu diakui sebagai pemilik seluruh negeri. Tidak ada pendeta atau kuil khusus dalam agama Tiongkok kuno. Upacara keagamaan dilakukan di udara terbuka. Berbagai jenis ilmu sihir, ilmu gaib, ramalan dan mantra juga tersebar luas di Tiongkok kuno. Gagasan agama Tiongkok kuno tentang roh alam dan leluhur kemudian diadopsi oleh Taoisme, Konfusianisme, dan Budha.
Agama Romawi kuno dicirikan oleh kepercayaan pada roh pelindung alam, kehidupan pedesaan, dan tenaga kerja pedesaan. Dengan terbentuknya negara Romawi, para dewa, yang jumlahnya sekitar 30 orang, menjadi dewa nasional, tidak terkait dengan wilayah tertentu. Jupiter dianggap yang tertinggi di antara mereka. Untuk semua warga Roma, kultus wajib ketiganya ditetapkan - Jupiter, Juno, dan Minerva. Kuil di Capitol didedikasikan untuk mereka (karena itu namanya - triad Capitoline).
Agama Slavia kuno adalah fenomena sinkretis yang kompleks dengan pemujaan leluhur yang berkembang, bentuk pemujaan terhadap alam, dan pemujaan pertanian komunal yang jelas. Dewa tertinggi di antara Slavia kuno adalah dewa guntur Perun. Mereka juga sangat menghormati dewa langit Svarog dan putra-putranya - dewa matahari, api dan angin - Dazhbog, Khors, Stribog, dewa "ternak" dan dewa kekayaan Veles (Volos), dewi Mokosh - pelindung pemintalan , tenun dan pekerjaan perempuan pada umumnya. Slavia Barat memuja dewa keberuntungan dan kebahagiaan Belbog. Nama-nama dewa suku Slavia seperti Svyatevit dan Rugevit, Radegost (di antara Lyubichs), Triglav (di antara orang Pomorian), dewi Siva (di antara orang Slavia Polabia), dll juga dikenal.Selain itu, personifikasi antropomorfik seperti Semik , Yarilo, Kupala, dll.
Meskipun para ulama telah lama memberikan perhatian yang cukup besar terhadap agama, perannya dalam sejarah masyarakat, pembentukan dan perkembangan kesadaran beragama, hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang refleksi filosofis dari kesadaran beragama. Para peneliti mulai menganalisis asal-usulnya dengan kurang rela, dan terlebih lagi, seperti disebutkan sebelumnya, mereka sering mengidentifikasi fenomena kesadaran beragama dengan agama. Sementara itu, menilik sejarah pemikiran filsafat memungkinkan kita menelusuri tahapan-tahapan pokok terbentuknya dan berkembangnya filsafat kesadaran beragama, yakni pencerminan model-model mentalnya yang terbentuk pada berbagai tahapan sejarah manusia.
Tentu saja, saat ini hampir tidak mungkin membicarakan rekonstruksi karakteristik kualitatif rinci dari kesadaran beragama pada tahap awal pembentukan dan perkembangannya. Namun, setidaknya ada tiga ciri esensialnya, menurut saya, dapat disebutkan dengan pasti. Yang pertama adalah bahwa kesadaran beragama pada waktu itu bersifat politeistik, yaitu dibedakan dengan pemujaan terhadap beberapa dewa, yang disebut berbeda-beda di berbagai tempat di planet tempat munculnya peradaban manusia. Karakteristik penting kedua dari munculnya kesadaran keagamaan manusia purba adalah keterbatasan fungsional para dewa, yang masing-masing, bisa dikatakan, bertanggung jawab atas bidang spesifiknya sendiri - dewa matahari, dewa petir, dewa petir, laut. Tuhan, dll. Ciri-ciri penting ketiga dari kesadaran keagamaan pada masa yang jauh itu adalah tidak adanya kesatuan dan subordinasi yang jelas di antara para dewa.
Ciri-ciri esensial ini, yang secara obyektif ada dalam kenyataan, juga terekam dalam filsafat kesadaran beragama yang baru muncul. Asal-usulnya sudah dapat ditemukan dalam kumpulan himne Veda India, terutama yang tertua - Rig Veda. Memahami secara kritis gambaran dewa yang terbentuk di benak orang-orang sezamannya, pemikir India kuno itu mengungkapkan keraguannya tentang keberadaan mereka. Secara khusus, berikut ini dikatakan tentang Indra, dewa guntur, kilat, dan badai petir:
"Saat Anda berkompetisi, nyanyikan lagu yang indah,
Untuk memuji Indra, [lagunya] benar, jika memang benar.
“Tidak ada Indra,” kata yang lain, “siapa yang melihatnya?
Siapa yang harus kita nyanyikan?"
Homer berupaya memahami kesadaran keagamaan orang Yunani kuno. Orang Yunani kuno, menurut Homer, percaya pada banyak dewa, percaya bahwa alam semesta terbagi antara tiga dewa bersaudara: Zeus memiliki langit, ruang dari awan hingga lapisan atas udara, eter - tak terukur dan sepi; Poseidon menguasai laut; Hades adalah penguasa kegelapan bawah tanah, tempat tersembunyi di bawah tanah tempat tinggal bayangan jiwa orang mati. Yang umum dari ketiganya, menurut kepercayaan orang Yunani kuno, adalah bumi dan tempat tinggal para dewa, Gunung Olympus.
Dalam Iliadnya, Homer mengatakan hal berikut:
"...Sang dewi memiliki darah abadi,"
Kelembapan yang mengalir di pembuluh darah para dewa yang diberkati:
Mereka tidak makan roti, mereka tidak mencicipi anggur, itulah sebabnya tidak ada Darah di dalamnya, dan orang-orang menyebut mereka abadi.”
Namun pandangan Homer, seperti Hesiod yang hidup setelahnya, harus digolongkan sebagai pandangan filosofis.
Sebenarnya, filsafat, sebagaimana diketahui, menelusuri sejarahnya kembali ke zaman kuno.
2. Kesadaran beragama: objek refleksi, ciri dan kekhususan
kesadaran beragama konservatisme supranatural
Filsafat kesadaran beragama muncul sebagai unsur pembentuk struktur filsafat sosial dan menurut kami dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penjelasan, penyebaran, dan penataan kembali struktur mental yang menentukan sikap seseorang terhadap dunia, dan dunia. dalam kaitannya dengan manusia, yang memanifestasikan dirinya dalam hubungan subjek agama dengan alam, satu sama lain, dengan berbagai elemen struktural organisme sosial tertentu pada tahap tertentu dalam perkembangan sejarahnya.
Filsafat kesadaran beragama mempunyai semua ciri-ciri umum yang menjadi ciri filsafat. Ia bertindak sebagai refleksi dan, dengan demikian, tidak membahas fenomena yang benar-benar ada, tetapi dengan refleksinya dalam kesadaran. Ini berkaitan, pertama-tama, dengan hubungan pemikiran dengan keberadaan, kesadaran dengan materi, dan merupakan sistem pandangan paling umum subjek tentang dunia dan tempat manusia di dalamnya, sehingga bertindak sebagai pandangan dunia.
Pada saat yang sama, filsafat kesadaran keagamaan dicirikan oleh sejumlah ciri. Hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa filsafat kesadaran keagamaan termasuk dalam filsafat sosial, yang kekhususannya dipertahankan oleh cabang filsafat yang kita minati. Berbicara tentang faktor-faktor yang menentukan kekhususan ini, perlu dicatat bahwa ini terutama merupakan ciri-ciri kognisi sosial. Bagaimanapun, subjek keagamaan, seperti halnya organisme sosial lainnya, baik itu individu, kelompok sosial, atau masyarakat secara keseluruhan, sekaligus bertindak sebagai objek kesadaran beragama. Mereka menciptakan sejarah agama dan mereka juga mengetahuinya, berkontribusi pada pembentukan model mental tertentu dalam kesadaran mereka, yang mereka refleksikan sendiri dalam proses analisis filosofis.
Ciri kedua filsafat kesadaran beragama, sebagai bagian dari cabang filsafat sosial, adalah pada dasarnya memuat aktivitas mental orang-orang yang mengejar tujuan-tujuan tertentu, kepentingan-kepentingan kelas sosial tertentu, suatu sistem nilai-nilai yang mapan, yang sampai taraf tertentu atau hal lain mempengaruhi jalannya analisis filosofis dan hasil-hasilnya.
Ada ciri-ciri lain dari filsafat kesadaran keagamaan, khususnya yang terkait dengan kekhususan objek dan subjeknya.
Objek kajian filsafat kesadaran beragama adalah model mental agama, salah satu aspek dan aspeknya. Bidang kesadaran sosial ini dibedakan oleh fakta bahwa ia didasarkan pada kepercayaan yang bersifat khusus - pada penggandaan dunia, pada keberadaan, seperti disebutkan sebelumnya, dua dunia - duniawi, duniawi, yang dirasakan oleh indera, dan dunia lain, surgawi, yang menentukan dunia duniawi itu sendiri dan perkembangannya, karena Tuhan bersemayam di sana, diberkahi dengan kualitas subjek absolut dengan kesempurnaan mutlak yang melekat dalam dirinya, pikiran eksternal yang memiliki kemahakuasaan, ketidakterbatasan, ketidakjelasan bagi pikiran. Jika refleksi model mental dunia pertama, dunia duniawi, verifikasinya melalui praktik untuk kecukupan terhadap fenomena yang benar-benar ada, khususnya sesuai dengan keyakinan agama, tidak menimbulkan pertanyaan khusus, maka verifikasi kebenaran model tersebut. dunia lain selalu dan tetap menjadi masalah, dan seringkali sama sekali mustahil, karena jalan menuju ke sana bagi pikiran manusia ditutup oleh kesadaran beragama. Keadaan yang menghambat perkembangan ilmu agama, membebankannya dengan ketentuan-ketentuan agama yang dulunya didalilkan, berubah menjadi dogma-dogma yang tak tergoyahkan, menghambat identifikasi arah optimal pengembangan ilmu agama, transformasinya menjadi pengetahuan yang dapat dipercaya tentang agama, tempatnya dalam budaya sebagai sebuah hasil kegiatan manusia, yang justru menjadi pokok bahasan filsafat kesadaran beragama.
Muncul pada tahapan sejarah tertentu, filsafat kesadaran beragama telah melalui jalur pembentukan dan perkembangan yang panjang dan sulit. Kami sekarang beralih ke analisisnya.
3. Struktur dan fungsi kesadaran beragama
Agama sebagai fenomena kehidupan sosial dapat dilihat dari berbagai sudut pandang: filosofis, sosiologis, psikologis, sejarah, teologis, budaya, etnopsikologis, serta dari aspek lain yang diperlukan untuk penelitian dan pemahaman yang lebih mendalam tentangnya. .
Untuk mengungkap kesadaran beragama, perlu diperjelas istilah “agama” itu sendiri yang mempunyai beragam penafsiran.
Ada banyak definisi tentang agama. Biasanya, sebagai ciri khasnya, mereka menyoroti kepercayaan pada dunia lain yang khusus, pada Tuhan atau dewa surgawi, dan tindakan terkait yang dilakukan orang-orang beriman untuk menghubungi dunia lain.
Konsep "agama" sendiri berasal dari bahasa Latin, diyakini bahwa istilah ini berasal dari kata kerja Latin relegere, yang dalam terjemahan literal berarti - pergi, kembali, merenungkan, merenungkan, mengumpulkan. Dalam hal ini, menurut Cicero, kata kuncinya adalah kata “ketakutan”.
Di sisi lain, Lactantius percaya bahwa agama sebagai sebuah istilah berasal dari kata kerja Latin religare - mengikat, membelenggu. Menurutnya, agama adalah hubungan seseorang dengan Tuhan, ketaatan kepada-Nya, dan pengabdiannya dengan cara yang khusus dan saleh. Pemahaman ini erat kaitannya dengan tradisi agama Kristen.
Dalam budaya Timur, konsep “agama” memiliki arti yang sedikit berbeda; hal ini didasarkan pada kata-kata berikut: din, dharma, chiao. - sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab sebelum zaman Islam, diterjemahkan sebagai kekuatan. - sebuah kata dari bahasa India kuno, diterjemahkan sebagai pengajaran, kebajikan, kualitas moral, tugas, keadilan - Kata Cina untuk mengajar.
Beragamnya bentuk keyakinan agama menjadi landasan obyektif multitafsirnya dalam definisi teoretis yang saat ini berjumlah sekitar 250.
Salah satu yang paling umum adalah definisi Johnstone: “Agama adalah sistem kepercayaan dan ritual yang digunakan sekelompok orang untuk menjelaskan dan menanggapi apa yang mereka anggap supernatural dan sakral.”
Dari sudut pandang lain, agama dipahami sebagai pandangan dunia, serta perilaku yang sesuai, yang ditentukan oleh keyakinan akan adanya kemutlakan supernatural.
Agama secara struktural merupakan fenomena yang agak kompleks. Meliputi: kesadaran beragama, kegiatan keagamaan, hubungan keagamaan, dan organisasi keagamaan.
Semua unsur ini mempunyai hubungan langsung satu sama lain. Kesadaran beragama tidak dapat eksis secara mandiri dalam dunia spiritual subjek, tanpa bersinggungan dengan bentuk-bentuk kesadaran sosial lainnya: moralitas, seni, ilmu pengetahuan, politik, hukum, serta komponen agama lainnya.
Semua agama di dunia muncul pada waktu yang hampir bersamaan. Prasyarat kemunculan mereka dapat dianggap melampaui keyakinan suku. Panggilan kepada Tuhan Yang Maha Esa, gambaran keabadian, ditentukan oleh kondisi kehidupan yang baru dan didukung oleh pihak berwenang. Semua agama dunia muncul dalam satu milenium - selama pergolakan sejarah besar, perubahan formasi, selama pembentukan kerajaan dunia.
Di dunia modern, merupakan kebiasaan untuk membedakan tiga agama berikut sebagai agama dunia: Budha, Kristen, Islam.
Menurut banyak peneliti, agama-agama dunia dicirikan oleh dakwah yang kuat (pengabdian yang kuat pada iman), aktivitas propaganda, dakwahnya bersifat antaretnis dan kosmopolitan, dan menarik perwakilan dari berbagai kelompok sosio-demografis. Agama-agama ini mengajarkan kesetaraan manusia.
Agama-agama di dunia, terlepas dari perbedaannya, memiliki momen-momen yang sama. Ahli budaya modern Erasov B. mengidentifikasi unsur-unsur kesamaan berikut:
adanya kepribadian yang kharismatik (Nabi atau Pendiri);
Kitab Suci atau Tradisi. Fakta keberadaan Teks Suci (Alkitab - dalam agama Kristen, Alquran - dalam Islam, Trip Ithaca - dalam agama Buddha);
dogmatika sebagai sarana pengorganisasian pengetahuan spiritual;
iman sebagai keselamatan jiwa dan integrasi umat beriman dari denominasi tertentu;
pemujaan berupa sarana yang menentukan kesatuan tindakan yang diabadikan dalam ritual.
Semua elemen ini, dengan satu atau lain cara, hadir di semua agama dunia. Biasanya, kemunculan dan perkembangan suatu agama dunia dikaitkan dengan wilayah geografis tertentu. Jadi, Budha adalah India Kuno, Kristen adalah bagian timur Kekaisaran Romawi, dan Islam adalah Arab bagian barat.
Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa pemahaman tentang agama itu beragam, namun semua konsep tersebut dan semua agama dipersatukan oleh satu kesamaan, satu tulang punggung – kepercayaan terhadap sesuatu yang gaib dan perilaku yang sesuai dengan keyakinan tersebut.
4. Kesadaran beragama modern: konservatisme dan tren perubahan
Kesadaran beragama dapat dinilai dari berbagai sumber. Basisnya terdiri dari gagasan keagamaan, inkarnasi, perasaan, harapan, harapan, dan keyakinan yang muncul secara spontan. Agama adalah “ilmu kehidupan, yang dikondisikan oleh pemikiran menyakitkan tentang kematian, tentang makna keberadaan manusia.”
Mengenal agama tertentu melibatkan penguasaan banyak perkataan, fakta, dan ritual. Pada hakikatnya hal-hal tersebut bukan merupakan pengetahuan agama dan kesadaran beragama. Untuk melakukan ini, kita perlu melihat banyak hubungan kapiler, seringkali tidak dicatat secara verbal, di antara mereka, yang memberi mereka karakter pandangan dunia yang tunggal dan holistik.
Kesadaran beragama dapat mencakup keyakinan keagamaan - ini bukan alasan abstrak tentang struktur alam semesta, tetapi kesadaran praktis yang menggeneralisasi pengalaman moral dan psikologis sehari-hari, ini adalah perasaan batin dalam hidup yang tidak dapat diungkapkan tanpa kehilangan dalam bentuk yang sangat terpisah. .
Di dunia modern, konflik sosial-politik yang signifikan sering kali diwarnai dengan nuansa agama, dan batas antara pihak-pihak yang bertikai sejalan dengan garis agama. Ada banyak contohnya: konfrontasi antara Yahudi, Kristen dan Muslim, Katolik dan Protestan, dll.
Agama adalah fenomena jiwa manusia yang sangat kompleks, dan generasi pemikir brilian belum sepenuhnya memahaminya, dan mungkin tidak akan pernah mampu mengungkap semua rahasianya dan memberikan jawaban yang cocok untuk semua orang. Oleh karena itu, paling sering Anda harus mengandalkan pemahaman Anda sendiri, pada akumulasi pengalaman penelitian, dan yang paling penting - pada fakta, pada realitas kehidupan, tanpa terbawa oleh pemikiran abstrak tentang perjuangan antara "terang" dan "kegelapan". Hal ini sangat penting mengingat situasi spiritual saat ini. Agama di zaman modern telah menjadi komponen yang hidup dan benar-benar berfungsi dalam pembentukan masyarakat dan perwujudan penghormatan lahiriah.
Kekhasan peradaban Eropa atau Kristen adalah pemujaan terhadap akal, rasionalitas, ilmu pengetahuan, pengusiran kegelapan, takhayul, dan prasangka dari masyarakat yang bentengnya adalah gereja.
Saat ini, di sejumlah daerah di mana penganut agama Ortodoks baru-baru ini mendominasi, mayoritas sudah menjadi penganut agama lain, terutama yang berasal dari luar negeri, formasi keagamaan baru telah bermunculan, terutama karena aliran misionaris yang cepat dan hampir tidak diatur. Seringkali muncul kasus ketika kesadaran keagamaan digunakan oleh kalangan penguasa untuk membangkitkan perasaan nasionalis. Manifestasi seperti itu sangat berbahaya, karena sering kali memberikan karakter kontradiksi abadi, yang bersifat sakral dan sulit diselesaikan dalam semangat saling berkompromi. Contohnya adalah seruan jihad – “perang suci”.
Perlu diingat bahwa agama bukan hanya sekedar seperangkat kepercayaan, tetapi juga tradisi, ritual, keterampilan berperilaku, dan hubungan khusus antar manusia. Oleh karena itu, bukan suatu kebetulan bahwa banyak hari raya dan ritual Ortodoks telah menjadi komponen akrab dalam cara hidup kita, meskipun pada saat yang sama sering kali kehilangan motivasi khusus pengakuan dosa.
Kesimpulannya, kita dapat melihat bahwa agama modern masih berbeda dengan agama yang ada berabad-abad yang lalu. Umat manusia telah mencapai tahap ketika kesadaran dirinya tidak dapat dibatasi pada absolutisasi pengalaman “penguasaan alam” duniawi, gagasan tentang akal, spiritualitas, kebebasan, yang terbentuk secara terpisah dari proses umum di Alam Semesta.
KESIMPULAN
Kesimpulannya, kita dapat mencatat bahwa agama itu sendiri, dan karenanya kesadaran keagamaan tertentu, muncul secara bertahap, pada gilirannya membentuk sikap-sikap tertentu terhadap perwakilan berbagai keyakinan agama.
Seiring berkembangnya masyarakat, perilaku masyarakat menjadi semakin sadar dan terarah, dan hal ini pada gilirannya menyebabkan peningkatan norma-norma peraturan moralitas – petunjuk umum dan norma-norma yang diterapkan seseorang sesuai dengan pengalaman hidupnya sendiri.
Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa agama modern masih berbeda dengan agama yang ada berabad-abad yang lalu. Seiring dengan pemahaman yang semakin profesional tentang landasan dan hakikat kesadaran beragama, perlahan-lahan bermunculan contoh-contoh budaya massa keagamaan yang dikomersialkan, menghadirkan agama dalam bentuk yang sama sekali berbeda.
Jadi, dalam kasus ini, dua hasil yang terkait dapat diramalkan. Pertama, meningkatnya pemahaman terhadap rahasia pandangan dunia keagamaan. Kedua, munculnya agama-agama tiruan yang secara populer dapat mengekspresikan gaya spiritual yang buruk, dan didukung oleh otoritas kitab-kitab suci yang tidak dapat disangkal.
Perlu dicatat bahwa setiap agama menghasilkan kesadaran keagamaannya sendiri-sendiri. Dan hal ini dapat menyebabkan berbagai jenis hubungan antar negara.
Dalam proses sejarah etnis, kebutuhan dan kepentingan baru selalu muncul dan terbentuk, untuk memenuhinya masyarakat nasional terpaksa mencari sumber daya, menciptakan sumber daya baru, atau mencapai redistribusi. Apalagi proses ini erat kaitannya dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dalam kepemilikan sumber daya material dan spiritual. Proses seperti ini dapat menimbulkan variasi dalam lingkup hubungan antaretnis, dan paling sering menimbulkan konflik.
Untuk menghindari ketegangan dan konflik, setiap bangsa dalam proses pembangunannya harus meningkatkan hubungan dengan komunitas etnis lain, mengembangkan bentuk-bentuk interaksi dan komunikasi yang memfasilitasi kehidupan bersama masyarakat, integrasi dan adaptasi mereka dalam lingkungan multinasional. . Pada saat yang sama, hubungan-hubungan ini dapat dikelola dan dioptimalkan, yang menjadi dasar pengembangan dan implementasi kemungkinan-kemungkinan untuk meramalkan dan melokalisasi konflik-konflik yang timbul dari beberapa kontradiksi yang muncul secara tidak terduga antar negara.
DAFTAR REFERENSI YANG DIGUNAKAN
1. Saudara B.S. Awal mula psikologi Kristen. M., 1995.
Claude Levi Strauss. Jalur topeng. M., 2000.
Krysko V.G. Psikologi etnis. M., 2004.
Magometov A.A. Hubungan antaretnis. M., 2004.
Oganov A.A., Khangeldieva I.G. Teori budaya. M., 2003.
Sodatov A.V. Studi Keagamaan. Sankt Peterburg, 2002.
Stefanenko T.G. Etnopsikologi. M., 2000.
Trofimov V.K. Mentalitas bangsa Rusia. Izhevsk, 2004.
Khotinets V.Yu. Identitas etnik. Sankt Peterburg, 2000.
Yablokov N. Dasar-dasar studi agama teoretis. M., 1994.
bimbingan belajar
Butuh bantuan mempelajari suatu topik?
Spesialis kami akan memberi saran atau memberikan layanan bimbingan belajar tentang topik yang Anda minati.
Kirimkan lamaran Anda menunjukkan topik saat ini untuk mengetahui kemungkinan mendapatkan konsultasi.
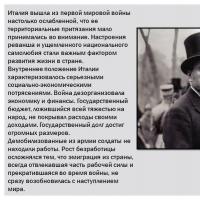 Kelahiran fasisme di Italia Fasisme dan korporatisme Italia
Kelahiran fasisme di Italia Fasisme dan korporatisme Italia Apakah ada masa depan bagi media cetak?
Apakah ada masa depan bagi media cetak? Sistem Tes Psikologi Myers-Briggs
Sistem Tes Psikologi Myers-Briggs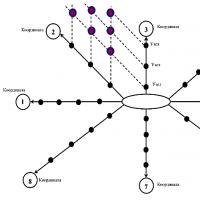 Kelas master menggunakan teknologi alat didaktik multidimensi Teknologi multidimensi di sekolah dasar
Kelas master menggunakan teknologi alat didaktik multidimensi Teknologi multidimensi di sekolah dasar Daftar dokumen untuk masuk ke Politeknik Barnaul
Daftar dokumen untuk masuk ke Politeknik Barnaul Tanda-tanda paling terkenal tentang garam Tanda-tanda Anda tidak bisa makan garam dari tempat garam
Tanda-tanda paling terkenal tentang garam Tanda-tanda Anda tidak bisa makan garam dari tempat garam Para rasul Rusia pertama. Rasul Rus'. Di salib manakah Santo Andreas disalibkan?
Para rasul Rusia pertama. Rasul Rus'. Di salib manakah Santo Andreas disalibkan?